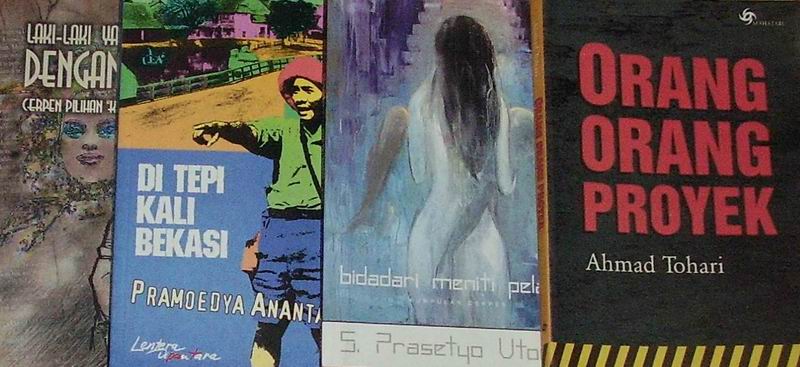Cerpen Raudal Tanjung Banua
Dimuat di Jawa Pos (03/07/2010)
KARYA seni adalah persimpangan jalan, tulis Milan Kundera1, saat ia kubaca dalam perjalanan. Bahuku terguncang karena batu dan lubang jalanan, tapi kuteruskan membaca, menyusuri sebuah pikiran. Jumlah jalan yang bertemu, lanjut Kundera, akan menentukan mutu seninya. Aku berpikir, jika kota dapat dikatakan sebagai karya seni, jalanan seperti apakah gerangan yang akan menentukan mutu sebuah kota?
Aku mengangkat kepala, menatap ke luar jendela dari bus yang berderak. Pohon-pohon, deretan rumah, dan semak-semak ikut bergerak. Bus kemudian memelan melewati pasar dengan simpang yang semrawut. Suara orang ramai seperti berebut masuk melewati kaca-kaca yang retak dan berdebu. Teriakan penjual obat pecah di tepi jalan. Penjual sayur mencangkung di muka keranjang. Lelaki tua menarik kambing dan seorang anak muda memarkir motor tanpa plat pas di moncong bus. Ketika akhirnya bus, susah-payah, lolos dari perangkap persimpangan, aku larut kembali memaknai simpang bagi sebuah kota.
Ya, mula-mula silangan jalan: pertigaan atau perempatan lalu tumbuh saling memberi; persimpangan mencipta kota, kota mencipta simpang-simpang. Sebuah tempat memiliki prosfektif untuk berkembang jika terletak di tempat bertemunya dua atau lebih ruas jalan. Ia akan jadi tempat pemberhentian, karena di situ mungkin ada rumah makan, bengkel kompresor, warung kopi, terminal bayangan, stasiun kecil, dan akhirnya nanti ruko, rumah bertingkat, swalayan. Lalu bakal muncul gardu polisi, papan iklan, lampu neon, traffic-light. Kemudian jalan baru dibangun, jalan lama terbelintang, simpang demi simpang bertemu; dari sekadar tempat berhenti, jadi tempat persinggahan, lalu jadi kota tujuan. Begitulah sebuah kota tumbuh. Tetapi soal mutu? Tunggu dulu. Kadang kupikir, kota dengan banyak simpang membuat kita tersesat karena terlalu banyak alamat, terlalu banyak nama-nama!2
Tapi, ah, tak ada yang sanggup menolak takdir simpang dari sebuah kota! Ia akan tetap terjaga, terus berjaga, bagi lintasan dan segala yang bakal singgah. Meski sebenarnya sebuah kota butuh persimpangan lebih ”hakiki”: jalan lempang ke kota yang lain. Bukan sekadar belokan dalam kota yang hanya cukup membuat seorang pedagang sate keliling berputar-putar dengan gerobak dorongnya. Maka, kota yang memiliki pedalaman, hulu atau ”mudiknya”, punya hilir atau ”induknya” sendiri –ditandai jalan yang panjang– akan lebih hidup dan berkembang. Atau kota lintasan, jalan pintas untuk menjangkau sebuah tempat lebih cepat, juga akan tumbuh lebih cepat. Namun simpang bukan sebatas darat, sebab juga ada jalan air dengan dermaga dan pelabuhannya. Itulah sebabnya, kota pelabuhan tidaklah berhadapan dengan kebuntuan laut mati. Pelabuhan sama dengan persimpangan, malah mestinya lebih banyak simpang, jalan air yang menghubungkan pulau-pulau, bahkan benua.
Aku tidak bilang kota tanpa simpang menerima kutukan jadi kota mati. Percayalah, kota tanpa simpang tapi terletak di jalur utama, jika pengelolanya tak hanya cerdik korupsi, niscaya tetap berdenyut hidup. Ia jadi persinggahan. Tempat transit, tanpa lengking pluit, jadi kota jasa dibutuhkan siapa saja. Tapi, adakah kota yang tak punya simpang di dunia?
***
PADA akhirnya, ada atau tidak ada persimpangan, sebuah kota akan menciptakan kota-kota kecilnya sendiri sebagai penyanggah. Lalu sadar atau tidak, keduanya saling memberi. Kota-kota penyanggah punya ”induk” yang mengharap limpahan berkah, dan kota yang disanggah punya ”mudik” yang diharap mengalirkan rezeki. Begitukah? Begitulah yang kupahami.
Memang, kota-kota penyanggah itu hanya kota kecamatan yang berkat persimpangan atau terletak di pelintasan, beroleh akses lebih baik. Lalu, seperti rumah kerang, tumbuh ia di antara kota kabupaten atau kotamadya yang lebih dulu tumbuh. Sebagian dari kota induk itu terus berkembang, sebagian lain terasa buntu. Apa pun keadaannya, kota penyanggah tetap berperan: selapis demi selapis, bagai menghikmati kulit bawang. Pendapatku ini cukup terasa jika kita menyusuri kota-kota kecil yang tumbuh subur di Pulau Jawa. Besarnya jumlah penduduk mungkin membuat ”kebutuhan” akan kota di Jawa jadi tinggi, sebab kotalah gudang kebutuhan dan pusat konsumsi. Itu satu hal. Tapi paling penting ialah akses jalan yang bagus, lapang, dan mulus. Jalur utama –termasuk jalur kereta– terus berbenah, dan lebih banyak lagi jalur alternatif, dan itu artinya simpang-simpang yang terbuka.
Kawan, aku tinggal di Jogja, di kota kecil Sewon. Di sini semua jalan beraspal, jumlahnya terus bertambah, seperti labirin, membuat kau bakal tersesat berputar-putar. Sebaliknya sangat mudah mencari jalan ke luar; arahkan saja kendaraanmu sesuka hati, nanti pasti sampai di jalan utama sebab jalanan kecil itu bertemu satu sama lain. Aku merasa beruntung tinggal di tempat yang jalannya bagus-bagus seperti di sini. Tapi kadang ngelangut sedih teringat banyak tempat yang sejak dunia terkembang belum pernah sekalipun tersentuh batu dan kerikil. Ah, Kawan, aku tak tahu ke mana rasa riang sekaligus murung ini kualamatkan. Rasanya tak mungkin kepada raja dan pangeran. Meski bagi sebagian orang Jogja dianggap pusat atau titik imbang Pulau Jawa. Kau toh pernah dengar konsep-konsep filosofis semacam Mangkubumi atau Pakubuwono yang maknanya bahkan merujuk kerajaan pedalaman ini sebagai ”pusat bumi”. Tapi aku tak banyak paham soal itu, sementara anggap saja tempat tinggalku titik tengah Pulau Jawa lebih karena fakta geografis. Fakta ini pun sebenarnya tak terlalu penting, kecuali hanya titik tolakku menjelajah kota ke segala arah.
Demikianlah, jika aku ke timur, aku akan bersua kota kecil penyanggah kota-kota sekitar. Yang terdekat Delanggu, kota kecil penghasil beras, menyanggah kota induknya, Klaten. Delanggu membangun ruangnya di ruas jalan Jogja-Solo, yang rasanya sebesar apa pun jalan penghubung selalu terasa tidak muat. Beberapa tahun lalu jalannya diperlebar, tapi kendaraan terasa makin banyak; rel kereta api commuter dibuat ganda, namun penumpang tambah sesak. Dan Delanggu tumbuh dengan beras aneka merk, wangi, dan pulen, meski pabrik karung goni yang dulu ia punyai sudah lama tutup, dan karung-karung plastik dengan mudah menggantikannya, semudah mendirikan toko-toko kelontong, rumah besar dan masjid warna-warni. Bersamaan dengan itu, sawahnya yang subur mulai ditimbuni tanah kapur, difondasi batu dan pasir dari Merapi; jadi ruang baru bagi kota yang berlari!
Jauh di timur, aku terkesan dengan Caruban, jalan pintas bagi bus-bus AC-eksekutif jurusan Jogja-Surabaya. Bangunannya merapat ke sisi jalan, membuat bus yang lewat seolah akan menggores dinding rumah dan toko-tokonya yang rawan. Sebaliknya, gang-gangnya terbuka lebar, becak dari pasar leluasa masuk ke kedalaman. Kurasakan, Caruban bagai sekotak brem, makanan khasnya yang manis-masam. Ia punya segala hal: dua pasar besar, stadion, terminal, bahkan gedung wakil rakyat Madiun, sebentar lagi jalan tol, tapi tidak mengubah wajah pengayuh becak di ujung gang.
Kota kecil dengan alun-alun besar ialah Bangil, kota yang tampak didirikan secara manual di antara Sidoarjo dan Pasuruan. Toko-toko di perempatannya banyak yang tua, bercat putih kelabu, sebagian berdinding kayu, tapi berkat itu tak mengenal karat dan ngengat. Simpang dan rel kereta, bersilangan bagai benang bordirnya di kain tapis. Selepas hutan jati Situbondo, aku bertemu Tenggir, tak ada di dalam peta namun ia sendiri sangat peduli pada peta; petunjuk arahnya lengkap, ke Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Di Jember yang basah, selepas Rambipuji, ada kota yang sama –tiada dalam peta– bernama Tanggul tapi sangat terbuka pada dunia; punya banyak tempat penukaran uang asing!
***
KE UTARA dari Jogja, aku bertemu Muntilan, penyanggah Magelang dan Mungkid yang baru tumbuh di kaki Borobudur. Deretan tokonya masif, nyaris tak bercelah, semua terisi bukan hanya tape ketan dan jajan pasar, tapi seluruh kebutuhan yang pokok dan tak pokok. Toko-toko itu pula agaknya yang membedakan Muntilan sebagai kota wedana di masa lalu, dan kota niaga di masa kini. Selepas pasar bersiaplah melihat kendaraan ngebut di jalan satu arah seolah melintasi sirkuit masa depan. Tak tahu, siapa akan menang; Muntilan yang tenang, atau para pelintas dari kota-kota sekitar yang bergegas.
Di Temanggung ada juga kota pelintasan, Parakan; pasarnya terus membesar, simpangnya mempercepat tujuan. Aku terkenang masjid tua kampung Kauman, dekat tikungan, seolah jadi penunjuk arah ke Pantura, melewati jalan naik dan menurun, tembus ke Weleri. Dan di jalur Pantura sendiri tumbuh kota-kota kecil di antara ibu kota kabupaten, jadi penyanggah yang geraknya kadang lebih hidup ketimbang kota utama. Juwana di Pati, Kaliwungu-Kendal, Comal-Pemalang, Palimanan-Cirebon, Lohbener-Indramayu. Apakah karena lebih kecil sehingga denyutnya gampang terlihat mata telanjang?
Menuju ke barat, aku singgah di Kroya, sebelum Cilacap. Di sini jalur kereta utama di Pulau Jawa seakan bertemu diam-diam, di bawah stasiun beratap baja. Turunlah, luangkan waktumu menempuh jalan-jalan kecilnya, kau bersua toko pakaian, kedai swalayan, warung soto yang nikmat. Angin sawah berembus mengangkut aroma lumpur, jerami padi, dan bebek-bebek. Malam hari, sehabis hujan, suara kodok akan menidurkan kota, dan deru kereta seperti menindih mimpi.
Lebih ke barat lagi, selepas Banyumas menjelang Purwokerto, aku kerap tergeragap disambut kota kecil yang manis, Sokaraja. Manis, serasa getuk goreng atau lukisan alamnya yang lembut di kanvas beludru, membuatku selalu rindu bertemu.
Jika aku menyerong agak ke utara, ke Brebes, akan kulewati kota kecil yang permai, dikelilingi sawah bertingkat, sungai dan bukit biru, berkabut nyaris kelabu. Bumiayu. Aku tahu, jumlah rumah yang bertengger di kaki bukit semakin banyak, sebagian mengarah ke puncak, membuat bukit-bukit remaja itu seperti anak sekolah yang mulai memikirkan lowongan kerja.
Lurus ke barat, kita sampai di Majenang. Di sini, rumah-rumah seperti kotak lebah tergantung di peternakan. Namun, suatu kali, terbangun dari lelap tengah malam, kusaksikan semua itu seperti peti rambu solok3 merapat ke bukit-bukit batu Tana Toraja. O, tidak! Aku menggosok mataku: ini bukan kota kematian, tapi kota kehidupan. Namun ketika tidur lagi, aku bermimpi: orang-orang seperti kumbang menggirik dinding batu! Apakah gambaran masa depan Majenang yang kelak menggempur bukit-bukit itu? Aku tak tahu.
Sebelumnya, kulewati dua kota di batas Jogja. Kutoarjo di Purworejo, dulu ibu kota Bagelan, kini denyutnya tidaklah padam; agen bus segala jurusan, jalan bersimpang ke dan kota-kota di dataran tinggi Dieng. Seperti keliaran arus sungai Jayanegara, Gombong di Kebumen terus tumbuh, penuh gairah. Dua rumah sakit swasta, pasar yang luas, hotel dan restoran, masjid indah di batas kota, melengkapi cabang jalan ke Banjarnegara dan Waduk Sempor.
Kawan, kotaku berhadapan dengan laut selatan yang ganas tapi berhati lembut, persis Nyai Roro Kidul. Karena itu, bukan tidak ada jalan ke selatan. Aku bisa saja menyusuri jalan Deandles dari Bantul sampai Kebumen, lalu berjumpa Ambal dan Ayah. Ambal punya sate berkuah tempe dan Ayah memiliki pasar ikan di muara sungai lebar, persis seorang ayah yang penyabar. Jalur lain melewati Wonosari atau Panggang, terus ke Purwantoro, kota kecil di tengah sawah yang menyanggah Wonogiri nun di lembah.
***
SINGKAT kata, setiap kota punya satu atau lebih kota penyanggah. Tentu juga dengan satu atau lebih alasan. Mungkin posisi, sejarah, atau segala sesuatu yang dimilikinya; stasiun, kebun, pelabuhan, tempat wisata, pabrik, dan lainnya. Maka, ia jadi kota kedua yang dirujuk setelah menyebut nama kota ”induk”. Sebutlah Sukabumi, ingatanmu melayang ke Pelabuhan Ratu, kota mungil di tepian teluk, di mana sukar membedakan kilau lampu resort atau cahaya mercusuar. Serang punya Merak dan Anyer, Tegal-Sidodadi, Semarang-Ambarawa, Cepu-Blora, Pare-Kediri. Begitu pula Kertosono di Nganjuk, Babat di Lamongan, Bululawang-Dampit-Turen di Malang, Klakah-Jatiroto di Lumajang, Leces di Probolinggo, Ambulu di Jember, Genteng di Banyuwangi, serta kota-kota yang kuceritakan tadi, begitulah seterusnya.
Ini tentu juga terjadi di bagian lain tanah air, meski tidak sesubur di Pulau Jawa. Seperti kubilang, selain penduduk, jumlah jalan sangat menentukan lahirnya sebuah kota. Barangsiapa ingin menumbuhkan kota, bangunlah jalan dan pelihara simpang-simpangnya!
Sadar akan hal ini, Pulau Punjung mulai memandang pelintasan dan simpang jalan tidak sekadar sampiran dalam dendang. Berkat lintasan, kini ia jadi ibu kota kabupaten baru di Sumatera Barat, Dharmasaraya, lepas dari Sijunjung. Ia berdamping dengan Gunung Medan, di mana berdiri megah warung makan ternama di Jalan Lintas Sumatera. Tak jauh dari situ, ada Kota Baru, pusat ekonomi Dharmasaraya, karena ia punya ”mudiknya” sendiri: jalan bersimpang ke daerah transmigran Sitiung. Memang pula, pelintasan tak selamanya bergairah. Kau tahu, penumpang bus banyak beralih ke pesawat, truk-truk kehilangan muatan, dan Jalan Lintas Sumatera yang menjadi urat nadinya (o, urat nadi semua kota!) rusak di mana-mana, diperbaiki tambal-sulam, seperti malam yang tak pasti dapat cahaya. Namun tetap saja lintasan lebih punya berkah. Coba, lihatlah Muaro, ibu kota kabupaten lama Sijunjung. Kota ini menjauh dari Jalan Lintas Sumatera, sedang simpangnya tak meyakinkan, sehingga membayangkannya saja sekarang aku disergap rasa lengang, bagai memandang pohon langsat merimba di ladang orang. Mungkin lain jika kotanya dulu Pematang Panjang, di tepi lintasan, aksesnya pasti luas seperti Bangko atau Muaro Bungo di Jambi.
Kita melompat ke Simpang Empat. Dulu ia penyanggah Lubuk Sikaping, Pasaman. Berkat simpang dan kebun sawit, tumbuh ia jadi ibu kota kabupaten baru, Pasaman Barat, menyusul Natal di Mandailiang. Namun menyalip Air Bangis dan Bonjol, dua kota penting sejak zaman kolonial. Mungkin di pantai Air Bangis kau masih mencium bau ikan dan kapal-kapal. Dan di Bonjol bayanganmu angslup di bawah garis edar matahari seperti pudarnya benteng dan parit masa lalu. Tapi percayalah, kebanyakan kota tumbuh dari modal masa kini: kebun sawit, pasar, pajak, retribusi, bank, dan pabrik-pabrik. Selain itu, kau akan termangu. Kecuali kotamu punya sesuatu untuk ditawarkan, seperti Duri di Dumai –jalan bersimpang ke Bagan Batu– punya kilang pipa-pipa besi menyedot minyak bumi. Tapi toh jalanannya tetap saja terkelupas sehingga terasa lengang bagai panas tengah hari. Atau, Koba di Bangka Tengah, kota timah yang dimekarkan jadi ibu kota kabupaten baru, tumbuh ambigu: papan iklan pemda dan perusahaan timah berebut ruang di gerbang kota. Tak tahu, siapakah yang berkuasa: pemerintah daerah yang masih muda, atau perusahaan timah yang tua bangka!
Di Bali, kota kecil Mengwi hidup di antara Denpasar dan Tabanan, meski lebih dari itu, apa yang membuatnya berkembang –trotoar dibangun, jalan satu arah diatur– tidak lain letaknya di dua arah tempat wisata: Bedugul-Tanah Lot. Mengwi sendiri punya Taman Ayun, di mana jalan alternatif juga mulus ke Ubud. Jadilah ia menyatu dengan dua kota utama yang mengapitnya. Beda dengan Seririt di Singaraja. Tak ada jatah kue pariwisata, tapi kota yang dihantam gempa tahun 1976 itu, terus bangkit mengandalkan simpang ”segara-gunungnya”; naik ke bukit memintas Tabanan, lurus menyisir pantai ke Amlapura dan Gilimanuk.
Binuang, kota kecil di antara Banjarbaru dan Rantau, di Kalimantan Selatan, menjadi kota persinggahan yang cukup ramai karena penambangan batu baranya. Di situ, ada tambang batu baru tua, Pangaron, dan tambang-tambang baru terus dibuka. Lubang jalanan, deru, dan derak truk, tidak menghalangi Binuang tumbuh, meski kadang tampak seperti seorang gadis yang menunggu dalam debu. Debu juga beterbangan di jalanan Wonomulyo, kota orang-orang trans di Polewali Mandar, Sulawesi. Tapi ia terus berdandan. Lihatlah, masjid dengan menara tinggi, seolah menghindar dari debu di bumi; kios di pasar dan toko-toko berbagai nama, membuatnya terasa lebih hidup ketimbang Polewali!
***
KADANG kupikir, kota kecil lebih gampang dirawat, besar sedikit merepotkan, jika sudah tumbuh besar, hati-hati, dia bisa memakan yang kecil, dan itu mencemaskan! Memang kota penyanggah bisa jadi kota utama, tapi siapa jamin peralihan status menyentuh piring nasi penghuninya? Kepanjen jadi ibu kota Malang, tapi pasar dan stasiunnya tetap sempit dan becek. Banjar di perbatasan Jawa Barat, sukses menyandang status kotamadya, menyalip kota induknya, Ciamis. Tapi, apa lebih berarti selain statusnya yang mengharu-biru itu? Banyak pula di antara kota ”induk” tak mau kalah, berpacu meraih status baru meski tak ada yang berubah. Tasikmalaya dan Klaten, kini punya wali kota, tapi apa pengaruhnya pada lapangan Dadaha atau pedagang lele dari Ceper? Tak ada, kecuali parkir lebih diawasi, Satpol PP lebih gaduh, swalayan di mana-mana, trotoar diproyekkan, dan lampu merah kian banyak saja.
Kawan, kau boleh mengagumi insting kolonial memilih tempat dan merancang sebuah kota. Tapi masa depan punya persimpangan nasibnya sendiri. Terbukti, kota penting yang dibangun kolonial di masa lalu, ternyata ditinggalkan. Banyumas, Lasem, Panarukan. Hasrat memutus mimpi buruk? Kurasa lebih sebagai hasrat mengambil sisi lain kolonial: penaklukan! Maka, lihatlah, Bandung dengan taman-taman besarnya dan Jakarta dengan kanal-kanalnya pun ”sukses” ditaklukkan pengelola kota sampai tidak ada yang bersisa…
Kupejamkan mata, berharap kota-kota kecil tumbuh sebagaimana kodratnya, tanpa hasrat menaklukkan. Ah, kini aku jauh di pesisir Sumatera, menyusuri daerahku yang merana. Sudah lama kulewati Painan, ibu kota kabupaten yang persimpangannya baru saja punya lampu merah. Mungkin lebih baik. Sebab simpang besar dengan banyak jalan, kadang membuatku sulit memahami mana jalan yang bernilai seni, mana yang sampah. Karya seni adalah persimpangan, kata Kundera, dan aku ingin membalik: persimpangan adalah karya seni –jumlah karya yang ”ditampilkan” menentukan mutu persimpangan!
Tak terasa, aku telah tiba di Tapan, kota kecil di perbatasan tiga provinsi: Bengkulu-Sumbar-Jambi. Sangat strategis, tapi bertahun-tahun tak ada yang cukup bermutu dari persimpangannya: jalanan rusak, wajah kota murung abadi. Sampai akhirnya kebun sawit dibuka berhektare-hektare, pabrik didirikan, jalanan ke Sungaipenuh dan Muko-muko mulai menggeliat. Tapi masih menyimpan kesedihan yang tak gampang terlihat, bagai suara kernet yang berseru, seakan jauh di masa lalu, ”Ke Jambi, ke Bengkulu! Tunggu bus lain dekat tugu.”
Aku tak peduli lagi bacaanku, langsung turun saat bus menepi. Sebuah truk lewat mengangkut bertandan-tandan kelapa sawit, seolah mengangkut impian Tapan ke masa depan. Di tengah kepulan debu, kulihat seorang lelaki melintas. ”Hoi, Kudal, jadi wa’ang datang?!” ia berseru di seberang jalan. Gigi-giginya hitam. Dialah suami kakak sepupuku, Uda Kidam. Sudah lama kami tak bertemu. Dan ketika ia menyeberang tersaruk dan agak bungkuk, aku membayangkannya sedang mengais masa lalu Tapan dengan tangguk udangnya di rawa-rawa yang luas; kini jadi kebun sawit seluas bumi, bakal jadi kota baru di muka bumi, o, penaklukan yang murni! ***
Rumahlebah Jogjakarta, 2009-2010