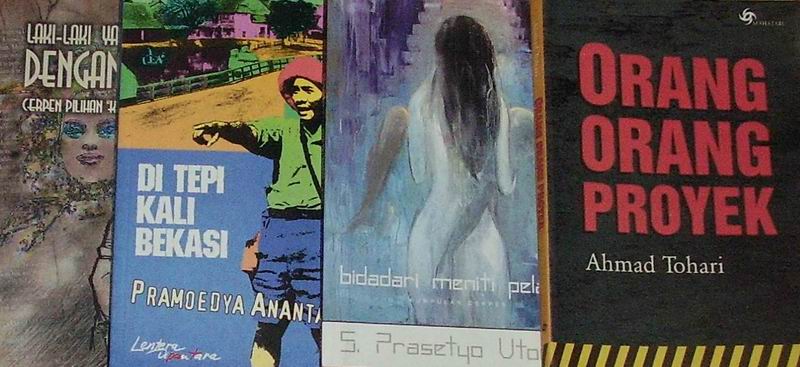Cerpen Adek Alwi
Dimuat di Jurnal Nasional (01/10/2010)
“AKU suka hujan,” kata perempuan di sebelah Bram, bak nyeletuk.
“Ya?” Bram menengok. “Oh, mengapa begitu?” susulnya buru-buru.
“Gemeretak suara hujan di atas genteng selalu membawaku ke mana-mana,” kata perempuan itu.
“Maksudmu, hujan membuatmu ingin muter-muter keliling kota?”
“Bukan.” Perempuan itu tersenyum, bagai baru sadar tak bicara ke diri sendiri. Kulitnya bersih, kuning dekat ke putih. Matanya tampak bagus. “Hujan membawaku ke masa lalu yang indah. Ke masa depan yang juga indah,” dia bilang.
“O.” Bram manggut-manggut, balas tersenyum.
Saat itu mereka di rumah kawan yang merayakan ulang tahun perkawinan dan gerimis tiba-tiba turun di luar. Perempuan itu teman nyonya rumah, Bram kawan tuan rumah. Di situ keduanya berkenalan.
Empat, atau lima hari kemudian Jakarta kembali basah. Kali ini benar-benar karena hujan, tidak lagi sekadar gerimis. Padahal sebelumnya cerah, tak tampak gabak di hulu bak disebut-sebut petuah lama itu. Bram dalam perjalanan pulang dan tiba-tiba dia teringat perempuan itu. “Halo, Ria,” sapanya di HP. “Ini saya, Bram. Apa kabar?”
“Baik. Bang Bram bagaimana, sehat?”
“Baik, sehat. Saya lagi di jalan. Kamu di mana?”
“Di rumah.”
“Lo, sudah pulang kantor?”
“Memang tidak masuk. Lagi malas.”
Bram ikut ketawa. Lalu, “Di sini hujan,” ia bilang. “Di tempatmu bagaimana?”
“Ini sedang deras-derasnya.”
“Oh. Saya tidak mengganggu perjalananmu bersama hujan, kan?”
“Belum berangkat.” Perempuan itu tertawa. “Malah bisa ditunda jika ada yang mampir.”
Bram mampir. Ya, di tengah hujan begitu. Pakaian dan rambutnya basah sebab dia harus berlari dari pinggir jalan ke rumah Ria, tetapi perempuan itu menyambutnya cerah, tidak seperti hari menyambut senja dengan hujan beserta langit yang muram-basah. Mata perempuan itu pun makin bagus saat bercakap. Dada Bram kian berdebar melihatnya. Aku tahu aku menyukai perempuan ini, bisik laki-laki itu di hati. Dan itu karena matanya.
Sebetulnya, tidak cuma mata perempuan itu yang memesona. Rambutnya juga. Hitam, subur, sedikit berombak dan ia biarkan tergerai melampaui pundak. Begitu pun tubuhnya. Terawat, membuat ia tak seperti 30-an tahun, juga punya anak. Perempuan itu singlet parent sejak suaminya wafat. Tetapi jika diperingkatkan, mata serta alisnya yang tak dicabut apalagi dicukur menempati peringkat teratas ketertarikan Bram. Alis perempuan itu lengkung rapi, asli, meneduhi matanya yang bagus. Rambut perempuan itu di peringkat kedua, Bram menegaskan di hati.
Setelah kunjungan itu dua atau tiga kali mereka pergi bersama; makan di resto di kawasan BSD, juga Bintaro, dan Bram tambah yakin dia tertarik kepada perempuan itu. Lebih dari tertarik, dia rasakan ada yang tumbuh di hati; ya, pada usianya yang tak muda lagi. Sesuatu yang indah, lembut, bikin hari terasa cerah.
“Saya menyayangimu, saya mencintaimu,” akhirnya ia berucap. Lelaki itu merasa kalimat itu tak sepenuhnya mampu melukiskan perasaan indah dan lembut itu, tapi ia tak dapat mencari ungkapan lain yang lebih tepat.
Perempuan itu tak membalasnya dengan kata. Dia biarkan jari digenggam, dan perlahan dia balas menggenggam. Ungkapan cinta memang tak selalu dibalas melalui ucapan, kata Bram dalam hati, meyakinkan diri bahwa perempuan itu pun memiliki perasaan indah serta lembut kepadanya. Lelaki itu tambah yakin dengan pendapatnya ketika hari-hari berlalu dan perempuan itu membalas SMS yang dia kirim.
“Saya pun menyayangi Abang,” tulis Ria. Hari-hari berikut dia tambah dan bunyinya jadi begini: “Saya menyayangi Abang. Abang jangan pernah lupakan saya.” Bram membalasnya bersemangat, “Tidak. Tak akan pernah. Percayalah.”
Juga pernah, usai mereka bercinta di luar kota Bram kemudian duduk di muka jendela, memandang ke luar. Hotel itu di pegunungan, sunyi dari bunyi kendaraan. Dan langit tampak cerah. Perempuan itu menghampiri dari belakang. “Kenapa Abang melamun?” dia bilang. “Menyesal?”
“Kok menyesal? Saya justru sedang di sebaliknya.”
“Ada apa di sebalik sesal?”
“Saya merasa dari hari ke hari rasa sayang saya terus tumbuh dan membesar.”
“Dan, itu masalah?”
“Saya takut. Hantamannya juga amat besar jika hubungan ini berakhir.”
“Siapa yang akan mengakhiri? Abang?”
“Saya jelas tidak.”
“Saya juga tidak,” balas Ria. “Saya menyayangi Abang. Sangat sayang.”
Bram menariknya dan mereka duduk bersisian. Rambutnya dia belai, dia cium keningnya. Bibir mereka bertemu. Ketika mereka toleh pula lewat jendela, eh, gerimis turun di luar. Sungguh tak diduga, tidak pakai aba-aba. Atau, lagi-lagi tak peduli pada ujaran lama “gabak di hulu tanda kan hujan” itu. Bram memeluk lagi, seraya berbisik, “Jangan pergi. Jangan pergi ke mana-mana bersama hujan.”
“Tidak,” kata perempuan itu. “Aku tak akan pergi. Toh ada Abang bersamaku.”
Akhir-akhir percakapan seperti itu tidak sekadar menyuburkan perasaan indah-lembut itu. Bram kadang-kadang jadi kelewat yakin hingga adakalanya dia lontarkan guyon-guyon yang sebenarnya hanya sedap diucapkan tetapi tidak sebagai kenyataan. “Ada dua kemungkinan dapat terjadi pada hubungan ini,” kata laki-laki itu, misalnya. “Pertama, kita tetap seperti ini dan suatu ketika nanti berakhir dengan happy.”
Perempuan itu tak menanggapi. Cuma senyum, matanya tampak makin bagus.
“Kedua, kamu jumpa dan jatuh cinta pada lelaki yang….”
“Jangan teruskan.”
Tapi Bram melanjutkan, “Umurnya jauh di bawahku, sedikit di atasmu. Kalian bisa disebut sepantar, malah serasi. Lalu, saat kita jumpa pula….”
“Jangan dilanjutkan,” perempuan itu kembali menukas.
Bram tetap bicara, “Kamu bilang: Abang, maaf. Hubungan ini tak dapat lanjut. Abang punya keluarga dan saya jumpa lelaki yang….”
“Stop,” sela perempuan itu. Ia susul, “Sebetulnya, itu yang Abang inginkan?”
“Tentu tidak,” balas Bram.
“Lalu….”
“Ah, itu cuma guyon, kok.”
“Tapi tidak baik. Juga menyakitkan.”
“Oh, maaf. Sudahlah, lupakan.”
***
Kemudian Juli datang, malah hampir berakhir. Musim hujan belum saatnya tiba. Tapi, kau tahu sekarang cuaca tak mudah dipahami. Empat hari hujan turun dari pagi kadang juga hingga petang, dan selama itu Bram bertanya-tanya apa yang tengah menerpa hubungannya dengan perempuan itu. Teleponnya tak pernah diangkat. SMS-nya tak dibalas. Di rumah, saat ia datangi, di tengah hujan, perempuan itu tak ada. Dia datangi ke kantor, juga di tengah hujan, rekannya bilang sedang ke luar. Ke mana Ria, perempuan itu? Pergi bersama hujan ke masa lalu yang indah? Ke masa depan yang juga indah? Sungguh bikin bingung. Menggelisahkan.
Hari kelima, tatkala hujan tidak lagi turun tapi langit tetap muram bagai wajah seusai tangis, tak disangka-sangka perempuan itu angkat telepon Bram. “Oh.” Lelaki itu mengatur napas dan pikiran yang berdesakan. “Kamu ke mana?”
“Tidak ke mana-mana.”
“Saya cari ke rumah, juga kantormu, tidak ada.”
“Saya ada, kok.”
“Telepon-telepon saya juga tidak diangkat.”
“Maaf.”
“Kenapa SMS-SMS saya tidak dibalas? Ada apa sebetulnya?”
“SMS? Mungkin tidak masuk.”
Bram mulai merasa ada yang tengah berubah, seperti hujan mulai mengingkari musim, juga tanda-tanda pada ungkapan lama itu. Setengah mengajuk, lelaki itu lalu bertanya, “Atau, barangkali ada laki-laki lain?”
“Ya,” jawab perempuan itu.
Oh. Jelas sudah. “Tapi, kenapa?”
“Sebab saya menyayangimu. Sebab saya sayang Abang. Hubungan ini tak bisa lanjut. Kita makin hancur jika terlambat mengakhiri.”
Itu kilah. Malah dusta. Sebab, “Apa dia lelaki yang sendiri?” tanya Bram. Dan perempuan itu bilang tidak.
“Jadi, dia pun sudah berkeluarga?”
“Hmm… ya.”
“Lalu kenapa?”
“Sudah, ya. Nanti saja. Maaf.”
Alangkah aneh, juga sulit dipahami. Persis hujan masa kini yang mengingkari dan tak lagi peduli pada musim. Lelaki itu sempat terpikir dia adalah musim yang kini terasa jadi renta.
Tiga bulan lewat dan selama 120-an hari itu Bram selalu ingat perempuan itu. Ia begitu diikat perasaan indah dan lembut. Soalnya aku memang menyayangi dia, ia bilang di hati. Amat menyayanginya. Dia pernah berpikir mengekspresikan perasaan indah dan lembut itu ke wujudnya yang konkret. Tapi, itulah. Perempuan itu tiba-tiba menghentikan, seperti hujan yang tiba-tiba turun menyabot semua rencana kita di saat siang cerah bermatahari.
Kini tiga bulan lewat, dan tiga bulan sesudah akhir Juli atau awal Agustus itu mestinya musim hujan. Tetapi itu dahulu. Kini hujan tak turun setiap hari. Langit tempo-tempo amat cerah. Dan bila hujan turun ingatan Bram pun kian subur pada perempuan itu. Semua yang lalu jadinya seperti gambar-hidup, bergerak kembali.
“Abang cemburu jika kuceritakan satu peristiwa dahulu bersama suamiku?” kata perempuan itu saat mereka melintas antara Ciawi-Bogor, dan hujan turun tiba-tiba.
“Tidak.” Bram justru iba karena perempuan itu demikian setia, bahkan kepada peristiwa dan orang yang sudah tiada, pada masa lalu. Perasaan indah-lembut di hati lelaki itu menjadi-jadi. Ingin sekali ia membahagiakan perempuan itu. “Ceritalah,” dia bilang.
“Di sekitar sini juga saat itu. Kami pulang dari Puncak, hujan turun mendadak. Saya gembira sekali, Abang. Dia tahu itu dan dia matikan musik. Saya lalu menyimak gemeretak suara hujan pada kaca serta atap mobil. Lantas, saya turunkan kaca jendela, julurkan tangan keluar. Oh, indah sekali, Abang. Saya tertawa-tawa senang. Dia ikut ketawa dan meminta saya hati-hati, jangan sampai tangan saya disambar mobil lain.”
“Kini kamu ingin menjulurkan tangan ke luar jendela?” tanya Bram.
“Saya ingin menyusupkan jemari saya di jemari Abang. Saya ingin menyimak suara hujan dan tak ingin pergi bersamanya. Saya ingin bersama Abang.”
Bram menggenggam jemarinya dengan sayang.
Lalu hujan betul-betul turun hampir tiap hari, seolah-olah kembali patuh pada musim. Empat atau lima hari berturut-turut. Televisi menyebut hujan merata seantero Jakarta. Ingatan Bram pun makin subur dan subur juga pada perempuan itu. Ia seakan menaruh harapan melihat perilaku hujan saat itu kepada musim. Siapa tahu hujan kali ini membawa perempuan itu ke masa lalu yang indah. Dan ia tekan nomor perempuan itu. Tak ada sahutan, sampai nada sambung berakhir. Dia pencet lagi, lagi…
“HP-mu berbunyi,” lelaki di sebelah perempuan itu berucap di seberang.
“Aku tahu.”
“Kok tak diangkat?”
“Aku sedang ke masa depan bersama hujan.”
Di luar, hujan terus menderu dan perempuan itu senyum lalu bergelung dalam pelukan lelaki itu.***
Jakarta, Sabtu 24.10.2009