Cerpen: Sawali Tuhusetya
Dada Tarmi naik-turun. Napasnya tiba-tiba terasa sesak. Kehadiran Surtini benar-benar membikin hatinya gerah. Sudah hampir sepuluh tahun ia malang melintang di dunia ketoprak tobong, belum pernah seorang pun yang mampu menggeser perannya sebagai rol dalam sebuah lakon. Yang membikin hatinya makin masygul, tidak ada seorang pun yang berupaya melakukan pembelaan-pembelaan. Betapa tidak sakit hati kalau tiba-tiba saja ia dicampakkan begitu saja, dibuang ke tong sampah.
Terbayang setiap kali pentas, ia bisa menghibur dirinya di tengah himpitan hidup yang berat dan sumpek. Ia bisa dengan mudah melupakan segala thethek-bengek urusan hidup yang serba ruwet. Baginya, panggung pertunjukan adalah istana yang mampu melambungkan mimpi-mimpi hidup yang serba enak dan menghanyutkan. Ia bisa dengan mudah memerankan permaisuri raja yang agung, putri istana yang cantik dan dimanjakan, pahlawan wanita yang dipuja banyak orang, pendekar yang dikagumi, atau bidadari yang dikelilingi banyak dayang. Tapi, kini kebahagiaan itu raib sudah. Tarmi menyedot napas panjang. Terasa benar, tenggorokannya amat berat seperti terganjal beban yang menyumbatnya.
Mengandalkan hidup sebagai pemain ketoprak tobong memang sangat tidak menjanjikan. Upah lima ribu rupiah sekali pentas hanya cukup sekadar pengganjal perut. Itu pun tidak setiap hari bisa didapatkannya. Bangku penonton sering sepi. Hanya diisi oleh beberapa gelintir orang yang rata-rata berusia tua. Menjamurnya hiburan murah di layar televisi telah membikin para penduduk malas beranjak keluar rumah. Para orang tua lebih suka memanjakan anaknya dengan imaji kemewahan dan kekerasan lewat tokoh-tokoh film, sinetron, atau telenovela yang kurang “membumi”.
***
Pentas ketoprak tobong benar-benar hampir sekarat. Loket karcis nyaris tak pernah dijamah sentuhan tangan para penduduk, kotor oleh timbunan debu. Triplek tobong sudah banyak yang bolong-bolong, banyak tiang penyangga yang hampir ambruk. Panggung pertunjukan pun sudah tidak layak untuk jingkrak-jingkrak para pemain. Sudah terlalu sering panggung dan tobong itu mengalami bongkar-pasang, dihajar panas dan hujan, beralih dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Makin lama makin keropos.
Meskipun demikian, semangat dan darah kesenian agaknya terus mengalir ke dalam tubuh para pemain. Mereka tak pernah surut dalam menghidupkan roh pementasan. Ditonton penduduk atau tidak, pertunjukan jalan terus. Apalagi, Bos Sadeli terus memutar otak untuk menghidupi pementasan dan perut para pemainnya. Lelaki separuh baya itu memang betul-betul memiliki kesetiaan luar biasa terhadap kelestarian seni ketoprak. Hampir sebagian besar keuntungan usaha mebelnya dikucurkan untuk membantu kelangsungan pementasan grup ketoprak yang sudah berusia hampir dua dasawarsa itu. Meski Bu Tarti, istrinya, pernah marah-marah, tapi Bos Sadeli tetap bergeming. Dengan segenap kelincahan dan kecerdikannya, ia berhasil menundukkan keangkuhan istrinya yang masih tampak sintal itu. Bahkan, kini istrinya mendukung penuh langkah suaminya dalam menghidupkan pertunjukan.
Dukungan istri Bos Sadeli ternyata membikin warna pertunjukan berubah. Para pemain lama yang dinilai sudah tidak layak pentas digeser, diganti pendatang baru yang dinilai mampu menarik penonton. Dagelan yang sukses mengocok perut penonton direkrutnya. Para niyaga dan waranggana dilatih rutin untuk mampu tampil maksimal dalam mengatur irama pertunjukan. Sutradara dan penulis naskah pun tak luput dari perhatian Bos Sadeli. Alur cerita dan penggarapan kisahnya menjadi lebih menyetuh perasaan penonton. Selain itu, layar yang menjadi setting pertunjukan diganti lebih gemerlap, berlapis-lapis. Dan yang cukup mencengangkan, Bos Sadeli telah berhasil mendirikan gedung pertunjukan yang kokoh dan mentereng.
Kini, para pemain tidak lagi direpotkan harus pontang-panting, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Untuk tinggal, mereka dibuatkan asrama sederhana di belakang gedung pertunjukan. Sebuah perubahan drastis yang jarang terjadi.
Gedung pertunjukan yang memadai, penggarapan kisah yang menarik, pemain yang berkarakter, dagelan yang kocak, panggung pertunjukan yang kokoh, garapan gending yang rancak dan berirama manis, maupun properti yang komplit, ternyata mampu menyedot animo penonton. Hampir setiap pentas, bangku penonton terisi penuh. Loket antre. Keuntungan terus mengalir ke kantong Bos Sadeli. Suasana gedung pertunjukan menjadi hidup. Apalagi, ketika mereka menyaksikan akting Surtini yang menggemaskan. Perempuan pendatang baru itu benar-benar tengah menjadi sang primadona. Ia seperti memancarkan pamor yang menerangi panggung. Lakon apa saja berhasil ia perankan dengan akting dan vokal yang nyaris sempurna. Rambutnya yang panjang tergerai, tubuhnya yang sintal semampai, wajah bulat telur dengan dagunya yang indah menggantung di bawah lesung pipitnya seakan mampu menaburkan aroma wangi yang menyembur-nyembur di bangku para penonton. Menghanyutkan.
Perubahan itu membikin hati Tarmi cemas. Nasibnya di grup itu makin tidak menentu. Perempuan yang suka tampil menor dengan taburan make-up berlebihan itu sering didapuk sebagai emban dengan peran seadanya. Ia merasa iri sekaligus dipinggirkan. Impiannya untuk menjadi seorang primadona yang diberi aplaus penonton, yang bisa menghidupkan gairah dan darah seninya di atas panggung seakan-akan telah berakhir.
Bos Sadeli dianggap telah berbuat tidak adil. Ketika grupnya terancam gulung tikar, Tarmi begitu setia meski dijadikan “sapi perah” untuk memikat hati penonton. Tapi ketika grup ini mampu menyedot penonton, tiba-tiba saja ia dibuang ke tong sampah. Huh, ini benar-benar tidak adil, protesnya dalam hati. Ia sering mengobral pergunjingan dengan sesama temannya, tapi mereka bersikap dingin. Cuek. Ia merasa tidak lagi dianggap sebagai pemain yang pantas diperhatikan. Untuk mengadu langsung kepada Bos Sadeli, sama sekali ia tidak memiliki keberanian. Hanya Mak Ginah, perempuan yang mulai tua dimakan usia yang selalu didapuk sebagai emban, yang dianggap memperhatikan dirinya. Itu pun hanya sebatas nasihat untuk pasrah menerima nasib.
“Sudahlah, Tarmi, kalau kita hanya cocok berperan sebagai emban, kenapa kita harus protes? Setiap orang punya peran sendiri-sendiri. Banyak orang yang ingin berperan sebagai raja atau ratu, toh tidak semuanya berhasil. Malah sering mengacaukan pertunjukan. Biar kita hanya sebagai emban, kalau kita perankan dengan segenap hati dan perasaan, pertunjukan bisa menjadi lebih hidup! Emban itu tak kalah menarik diperankan meski dibandingkan dengan permaisuri!”
“Tapi, Mak! Pak Sadeli telah berlaku tidak adil. Aku sudah bertahun-tahun menjadi rol dengan imbalan seadanya, lha kok tiba-tiba diturunkan begitu saja justru ketika ramai penonton! Apa tidak keblinger itu?”
Mak Ginah dapat memahami perasaan Tarmi, tapi tak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap wajah Tarmi yang suntrut dan berkabut.
***
Malam itu penonton kembali berjubel. Tepuk tangan dan suit-suit penonton tak henti-hentinya bergema, menggoyang gedung. Apalagi lakonnya mengangkat kisah percintaan Rara Mendut dan Pranacitra yang melegenda itu. Para penonton tampak hanyut mengikuti alur cerita. Mereka makin terpesona saat menyaksikan akting Surtini. Perempuan muda bertubuh sintal itu seperti benar-benar menjelma menjadi Rara Mendut yang sesungguhnya. Gerakan bibirnya yang merekah saat menyedot rokok, liukan tubuhnya yang lentur dan lincah saat menolak rayuan Tumenggung Wiraguna, atau vokalnya yang menggemaskan saat mendendangkan gending-gending asmara bersama Pranacitra, melambungkan khayal penonton ke tempat yang jauh. Aplaus dan tepuk tangan berkali-kali membahana. Namun, semua itu seperti ledakan bom yang meluluhlantakkan hati dan perasaan Tarmi.
Tidak seperti biasanya, kali ini Tarmi didapuk menjadi istri Tumenggung Wiraguna. Ketika tampil di panggung, pikirannya terpecah. Di layar benaknya hanya muncul bayangan Surtini yang dianggap telah merampas kebesaran namanya. Tapi, tepuk tangan penonton makin riuh ketika ia melabrak Surtini dengan amarah dan emosi yang memuncak. Ia dianggap berhasil memerankan istri Tumenggung Wiraguna dengan baik.
Panggung tiba-tiba berubah muram dan tegang. Penonton terhenyak. Mereka melihat adegan istri Tumenggung Wiraguna dengan emosi yang meledak-ledak menjambak rambut Rara Mendut yang panjang tergerai. Surtini mengaduh kesakitan, tapi sia-sia. Tarmi makin kuat menjambaknya. Bahkan, ia memaki-maki dengan kata-kata kotor, menyumpah-nyumpah.
Tarmi makin kalap. Rambut panjang Surtini dipilin-pilin, lantas dengan kekuatan penuh tubuh Surtini dibanting, terjerembab di atas panggung. Surtini terpekik dahsyat. Tarmi masih terus berakting. Wajahnya garang dan liar. Dengan bola mata menyala-nyala, tiba-tiba Tarmi melolos sebuah pisau, lantas dengan kecepatan tak terduga dihunjamkan ke perut Surtini. Darah segar menyembur-nyembur membasahi panggung. Penonton menjerit, riuh, kacau. Beberapa orang berlari menuju panggung, menjinakkan keganasan Tarmi yang masih terus menghunjamkan pisaunya ke tubuh Surtini.
Alur kisah berlangsung di luar skenario. Kematian Rara Mendut bukan lantaran bunuh diri, melainkan dihabisi oleh istri Tumenggung Wiraguna. Tubuhnya tergeletak mengenaskan di atas panggung dengan luka arang keranjang. ***

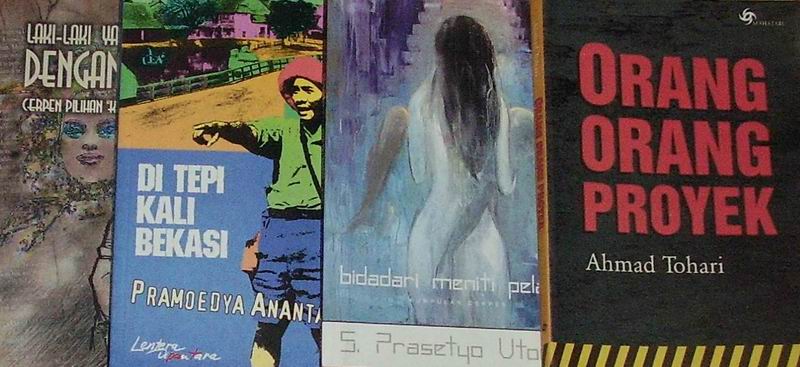
Silakan kalau ada teman-teman yang ingin mengomentari cerpen ini!
saya izin berkomentar pak sawali,,,
memang benar primadona banget untuk cerpen ini>>>