Sepekan belakangan ini, aktivitas ngeblog saya (nyaris) tersendat. Setelah melakukan monitoring implementasi KTSP SMP berstandar nasional (SSN) di kota Tegal, Selasa (8/12/2009), Rabu-Jumat (9-11/12/2009), saya mesti mendampingi anak-anak SMP Terbuka bersama rekan-rekan sejawat yang sedang melakukan karyawisata ke ibukota, sebuah kota megapolitan yang selama ini hanya bisa disaksikan anak-anak melalui layar TV butut di rumahnya. Maklum, anak-anak SMP Terbuka, dari sisi ekonomi memang mengalami hambatan. Jelas, sebuah kesempatan yang mahal apabila mereka bersama-sama bisa datang untuk menyaksikan gebyar Jakarta yang mewah dengan segenap asesoris kehidupannya yang (nyaris) serba hedonis, konsumtif, dan materialistik. Setidak-tidaknya, mereka bisa melihat secara langsung atmosfer sebuah kota yang menjadi pusat segala “peradaban” modern dan global itu.
Pendampingan karyawisata ini membuat saya kurang bisa intens ber-blogwalking ria ke rumah-rumah sahabat, bahkan saya tidak bisa hadir dalam acara Diskusi dan Peluncuran Buku “Suicide” karya Mbak Latree Manohara di Semarang, tepatnya di Ruang Loby Gedung Ki Narto Sabdo, Jalan Sriwijaya 29, 10 Desember 2009, pukul 19.00 WIB. Padahal, ada Mas Aulia A. Muhammad dan Triyanto Triwikromo, yang akan tampil sebagai pembedah yang dimeriahkan dengan pentas perform arts dan baca cerpen. Padahal, undangan dan buku bercover gelap tersebut sudah saya terima pada H-2. Padahal … Hmm … sungguh, saya sedih tidak bisa hadir dalam sebuah ruang diskusi yang bisa memicu adrenalin untuk larut dalam atmosfer yang “nyastra” banget itu. Saya sudah amat lama merindukannya.
Namun, apa mau dikata. Demi memberikan support kepada anak-anak, saya tak kuasa menolak ketika terpaksa harus memupus keinginan saya untuk hadir dalam diskusi dan peluncuran buku itu. Untuk meredam kesedihan, saya berjanji untuk me-review kumpulan cerpen menarik ini. Tak berlebihan kalau saya mesti menenteng buku kumpulan cerpen (kumcer) perempuan kelahiran Wonogiri, 20 Agustus 1976 itu, untuk menemani perjalanan saya bersama anak-anak.
Judul Buku: Suicide
Pengarang: Latree Manohara
Editor: Dwicipta/Agunghima
Penerbit: Gigih Pustaka Mandiri, Yogyakarta
Cetakan Pertama: Agustus 2009
Tebal Buku: xiv + 112
Seperti biasa, saya selalu membaca kata pengantar lebih dahulu ketika membaca buku baru. Dari situ, saya akan mendapatkan gambaran umum tentang isinya, bahkan bisa jadi akan menemukan “kata kunci” yang bisa saya gunakan untuk memasuki satu demi satu substansi materi yang didedahkan sang pengarang. Demikian juga halnya ketika membaca buku Latree Manohara ini. Dan, tiba-tiba saja saya tertarik membaca penggalan kata pengantar yang ditulis Dwicipta berikut ini.
Semula saya membaca sosok Latree Manohara sebagai tokoh fiksi yang tersekap pada ironi-ironi menyedihkan kehidupan populer yang menjerat sebagian besar manusia. Ia menulis prosa dan puisi dengan gaya populer, dengan tema-tema kehidupan populer di sekitarnya, dengan bahasa populer yang dengan sangat mudah dipahami oleh semua orang bahkan berkesan menggelikan bagi para pengagum prosa dan puisi yang serius. Dan pada saat yang sama, ia menjalani dinamika hidup yang tak jauh berbeda dari apa yang ia tuliskan dalam prosa dan puisinya.
Namun dalam pembacaan kedua, saya menemukan logika tokoh internal Latree Manohara: sebagai orang yang terjebak pada kehidupan populer, ia membaca dan memaknai kehidupan dan dunia ini dari sudut pandang kehidupan populer itu. Katakanlah sebuah kesaksian atau pengakuan tanpa malu-malu, bahkan penuh martabat, dengan menegakkan dan menegaskan kedirian.
Jujur saja, pernyataan Dwicipta cukup membantu saya dalam upaya memahami cerpen-cerpen yang terkumpul dalam Suicide yang selama ini saya memang jarang mengikuti dinamika Latree Manohara dalam berproses kreatif. Maka, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, saya jadi cukup nyaman ketika mencoba membaca dan menikmati 13 cerpen (Alarm 07.30, Hidup Ini Membuatku Terpana, Menunggu, Please Deh, Cin …, Reinkarnasi, Suicide, Kondom, Kesentil, Dul Kamdi, Silentium I, Silentium II, Antrean Kematian, dan Sabtu Sore yang Mendung) yang terkumpul dalam kumcer yang diterbitkan Gigih Pustaka Mandiri (2009) setebal xiv + 112 ini.
Sketsa Kehidupan
 Membaca ke-13 cerpen ini, saya seperti menyaksikan sketsa kehidupan yang kaya dimensi dan sarat konflik. Ibarat seorang dalang, perempuan yang sekaligus menjadi ibu dari ketiga anak tercintanya itu, bebas mempermainkan tokoh-tokohnya sesuai dengan selera intuitifnya yang tengah bermain-main di layar imajinasinya. Tokoh-tokoh cerita bisa diposisikan mancala putra-mancala putri dan manjing ajur-ajer dalam tikaman dimensi ruang dan waktu. Suatu ketika, sang tokoh aku bisa menjadi sosok anak-anak yang mengundang iba, tetapi pada saat yang lain, bisa menjelma menjadi sosok perempuan atau laki-laki perkasa yang sanggup mengatasi berbagai tekanan hidup yang berat, dan sekaligus juga sanggup menjadi saksi berbagai peristiwa hidup yang ironis, tragis, atau sarat dengan parodi hidup.
Membaca ke-13 cerpen ini, saya seperti menyaksikan sketsa kehidupan yang kaya dimensi dan sarat konflik. Ibarat seorang dalang, perempuan yang sekaligus menjadi ibu dari ketiga anak tercintanya itu, bebas mempermainkan tokoh-tokohnya sesuai dengan selera intuitifnya yang tengah bermain-main di layar imajinasinya. Tokoh-tokoh cerita bisa diposisikan mancala putra-mancala putri dan manjing ajur-ajer dalam tikaman dimensi ruang dan waktu. Suatu ketika, sang tokoh aku bisa menjadi sosok anak-anak yang mengundang iba, tetapi pada saat yang lain, bisa menjelma menjadi sosok perempuan atau laki-laki perkasa yang sanggup mengatasi berbagai tekanan hidup yang berat, dan sekaligus juga sanggup menjadi saksi berbagai peristiwa hidup yang ironis, tragis, atau sarat dengan parodi hidup.
Begitulah gambaran umum kisah-kisah pendek yang terangkum dalam kumcer ini. Agaknya, Latree Manohara tergolong pengarang yang tak mau terbebani dalam genre cerpen tertentu. Ia bisa berkisah tentang persoalan remeh-temeh hingga ke persoalan yang rumit dan kompleks. Dengan gaya ucap yang lincah dan cair, Latree Manohara bisa bercerita apa saja, tanpa beban literer tertentu. Dengan kata lain, Latree Manohara sanggup meng-konkret-kan persoalan-persoalan abstrak melalui narasi, deskripsi, dan dialog yang lincah-mengalir; bukan sebaliknya, seperti yang dialami oleh sebagian besar penulis cerpen; mengungkapkan persoalan yang konkret dan terang-benderang menjadi sesuatu yang abstrak dan serba gelap.
Dalam “Suicide” yang menjadi titel kumcer ini, misalnya, dalam amatan awam saya, sesungguhnya Latree Manohara sedang membidik sebuah persoalan berat yang dihadapi manusia metropolis ketika deraan hidup sedang menelikung sang tokoh. Namun, dengan gaya yang lincah, Latree Manohara sanggup menuturkan kisah berat itu secara apik dan enak dibaca. Tokoh “aku” yang menjadi korban kebiadaban nafsu seorang bajingan dan harus melahirkan bayi yang tidak dikehendakinya, didera depresi berat hingga terpaksa harus membunuh bayinya. Akumulasi perasaan berdosa, apalagi Bang Rahman yang amat dicintainya, dianggap tak pernah lagi memedulikan dirinya, membuat si “aku-Vi” nekad untuk bunuh diri. Namun, berkali-kali pula, selalu ada peristiwa lain yang bisa menyelamatkan nyawanya.
Upaya bunuh diri yang terakhir kali mempertemukan si aku-Vi dengan Bang Rahman yang memberikan kado sebuah cincin pernikahan ketika si aku-Vi tengah berada di puncak konflik psikis yang menderanya. Dengan dialog berbalut suasana religi, berkali-kali Bang Rahman dan keluarganya mengingatkan si aku-Vi untuk ber-istighfar dan berpaling lagi pada jalan Tuhan.
“Istighfar, Vi… Jangan kamu putar balik keadaan seperti itu. Kamu tahu kamu bisa bersandar pada-Nya sejak mula. Allah akan membantumu berdiri lagi dari keterpurukan…”
“Terlambat, Bang … terlambat. Aku sudah tidak sanggup lagi menanggung derita…” (hal. 70).
Sebuah dialog yang lincah dan cair, terlepas dari beban untuk menggurui. Dalam ending, Latree Manohara agaknya juga bukan penganut genre cerpen konvensional. Dia sengaja menggantungkan akhir kisah untuk memberikan ruang penafsiran kepada pembaca.
Dari 13 cerpen yang dihadirkan dalam buku ini, tokoh-tokoh yang bermain di dalamnya sebagian besar merupakan manusia-manusia global yang tergencet berbagai persoalan kekinian dengan mendedahkan konflik psiko-sosial yang begitu rumit dan kompleks. Dengan balutan gaya surealis, Latree Manohara dalam “Alarm 07.30” (hal. 1-5) bertutur tentang konflik si aku lirik dengan jam wekernya yang bermasalah dan pada saat yang lain, sang weker bertutur seperti layaknya manusia tentang perbuatan yang dia lakukan. “Hidup Ini Membuatku Terpana” (hal. 7-15) bertutur tentang masa kecil si aku lirik yang miskin dan Mbak Eny yang kaya raya. Namun, ketika dewasa, dinamika peradaban membuat atmosfer hidup menjadi amat kontras dan paradoks. Mbak Eny tenggelam dalam kehidupan rumah tangga yang amburadul, sedangkan si aku sukses dengan kehidupan keluarga bahagia.
Tentu saja, masih ada beberapa cerpen lain yang menarik untuk dibaca dan dinikmati. Persoalan-persoalan global yang rumit dan kompleks dengan amat sadar diangkat Latree Manohara ke dalam cerpen-cerpennya sebagai upaya sang pengarang untuk merefleksikan kenyataan-kenyataan hidup yang penuh ironi, tragis, dan juga sarat dengan parodi. Latree Manohara sengaja membiarkan tokoh-tokohnya bermain secara “liar” tanpa tendensi tertentu. Ibarat seorang fotografer, agaknya alumnus UNDIP 1998 yang kini bekerja sebagai PNS di Pemprov Jateng ini berupaya membidik berbagai fenomena hidup manusia masa kini dengan berbagai kompleksitas persoalan hidupnya apa adanya dengan memosisikan diri sebagai “si aku lirik” yang serba tahu terhadap semua perilaku tokoh sampai detil dan elaboratif. Meski demikian, pembaca diberikan kebebasan untuk memasuki ruang penafsiran sesuai dengan selera estetik dan gaya literernya masing-masing.
Yang agak tampil beda mungkin cerpen “Antrean Kematian” dan “Sabtu Sore yang Mendung”. “Antrean Kematian” (hal. 97-107), dalam pandangan awam saya, tergolong cerpen yang sarat dengan kritik sosial ketika manusia masa kini terhipnotis oleh budaya massa yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pendekatan medis dalam penyembuhan penyakit. Situasi seperti ini membuat ayah tokoh “aku” harus menjadi korban antrean di sebuah rumah seorang tabib pengobatan alternatif. Ia tak kuasa lagi menghadapi massa antrean yang beringas ketika jarak sejengkal pun menjadi amat berharga yang diyakini bisa menjadi ruang penyelamatan nyawa. Sedangkan, “Sabtu Sore yang Mendung” (hal. 109-112) yang sekaligus menjadi penutup kumcer, mengisahkan seorang anak bernama Bayu yang terkena sindrom halusinasi kerinduan terhadap ayahnya yang tengah merantau. Begitu kuatnya cengkeraman kerinduan itu sampai-sampai Bayu tak lagi bisa menikmati dunia bermain yang sah menjadi miliknya, bahkan di setiap ruang dan waktu, dia terus dibayangi wajah sang ayah yang membadai dalam layar halusinasinya.
Sebuah kumcer yang menarik. Selalu muncul suspense pada setiap kisah yang dituturkan. Dengan gaya tutur yang lincah, Latree tidak terbebani kode bahasa, sastra, atau budaya yang acapkali menelikung para pengarang kontemporer yang merasa dirinya “paham” dunia literer. Dengan dunia teknik sebagai basis keilmuannya, Latree justru sanggup menanggalkan batasan-batasan tentang sastra dan stilistika yang sering menjadi belenggu dalam berproses kreatif. Ia bisa bertutur apa saja dengan bebas dan tanpa beban. Oleh karena itu, Latree Manohara akan sanggup menerobos lorong-lorong imajinasinya hingga batas tak terhingga ketika dia masih berkenan untuk menjadi saksi berbagai fenomena hidup yang mencuat di atas panggung kehidupan sosial melalui gaya bertutur yang lincah dan mengalir yang sudah jelas-jelas menjadi miliknya ke dalam tuturan kisah yang liar dan mencengangkan. ***

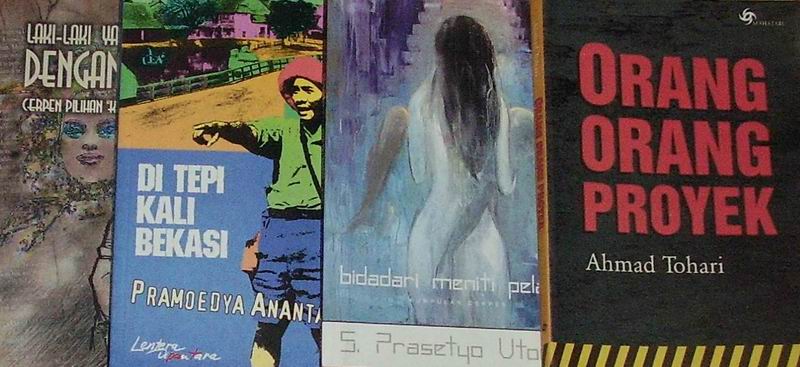
hidup memang banyak pilihan ya pak, tapi mendampingi anak2 didik ke jakarta nampaknya biasa bagi sang pendidik sejati … dan ternyata benar, tanpa hadir bedah bukunya pun pak sawali mampu membedah sendiri buku tsb di blog ini …. selamat !
hehe … itulah repotnya, mas hatta. terpaksa saya mesti mengikuti anak2 sambil membawa buku kiriman mbak latree itu, hehe …
nama pengarangnya manohara, mungkin kalo si manohara tidak terkenal, nama manohara tidak akan dipakai oleh mbak latree ini (perkiraan saya)
@riFFrizz, saya sudah memakai nama ‘manohara’ sejak lahir (which is 17 tahun sebelum ‘manohara yang itu’), dan tercantum di akta kelahiran, ijazah TK-SD-SMP-SMA-S1. juga di banyak piagam, KTP, SIM, buku rekening bank, ATM, kenggotaan di swalayan, serta semua Dokumen, SK dan Surat Perintah di tempat saya bekerja.
.-= Baca juga tulisan terbaru Latree berjudul "Dari Peluncuran ‘SUICIDE’" =-.
@riFFrizz,Yuupzzz bukan karena aq ada kesamaan nama…tetapi aq tahu sendiri bahwa Latree …bernama lengkap Latree Manohara Coz dia adalah adik tingkatku walau beda Fakultas…..di daftar gaji sebagai PNS pun nama Dia Latree Manohara…kalo dia cuma cari sensasi otomatis dia gak bisa ambil gaji…..bagi yang comment anda menyinggung perasaan dia dan terlebih orang tuanya yang telah menganugerahi nama manohara.
@Syam Manohara, Itu nama asli di daftar gaji dia sebagai PNS pun nama dia Latree Manohara…..kalo dia cari sensasi dia gak bisa ambil gaji….aq tahu dia karena ada kesamaan nama dan dia adik tingkatku walau beda Fakultas…
hehe … mas rifky jangan keliru, ya. nama latree manohara sudah ada jauh sebelum nama manohara itu jadi isu publik, kok, hehe …
@Sawali Tuhusetya, keliru deh saya pak, jadi malu nih, jadi itu nama asli ya !
gpp, mas rfiky, yang penting sekarang dah tahu, kan?
Buku yang menarik tampaknya ya Pak, nanti baca deh, akan saya tulis komen saya tentang buku itu disini, setelah saya baca :”>
.-= Baca juga tulisan terbaru Rindu berjudul "Blog ini DITUTUP" =-.
memang menarik, mbak rindu, mangga, silakan kalau ada waktu cari bukunya.
kirain suicide bomb.. itupun juga sarat konflik.. pelakunya menganggap itu bukan putus asa, tapi saya sependapat dengan yang menyatakan bahwa mereka itu putus asa dalam berdakwah, kurang sabar..
kalau ini beda, mas danang. ini judul cerpen yang sekaligus menjadi titel bukunya, hehe …
namanya manohara haha jadi inget…..
.-= Baca juga tulisan terbaru Reza Fauzi berjudul "Sesat dan Runtuhnya Teori Darwin" =-.
hmmm … nama latree manohara ndak ada hubungannya dg mantan istri pangeran kelantan, mas reza, hehe …
terima kasih, pak guru.
.-= Baca juga tulisan terbaru Latree berjudul "Dari Peluncuran ‘SUICIDE’" =-.
sama2 mbak latree. hanya tulisan seperti ini yang bisa aku posting.
Maaf Pak Sawali, kalau comment saya kali ini nggak bisa “nyastra”
Begitulah kalau Pak Sawali piknik.
Sambil “klencer”, bisa sambil ngreview “kumcer”… 😀
hehehe … pak mar memang selalu saja lincah bermain kosakata. “cer” sama “cer”, kok bisa?
buku yang menarik pak, sayangnya anggaran untuk beli buku sekarang dipangkas, untuk hal-hal lain yang lebih diutamakan.
.-= Baca juga tulisan terbaru sunarno berjudul "Dzikir" =-.
hehe … gpp, mas narno. mudah2an nanti ada jatah utk beli buku, hehe …
ya sebuah cerita dari sudut pandang sendiri memag akan meghasilkan sesuatu yang beda dan unik,
dan bukankah setiap orang punya beda yang cara mengungkaplannya tentu saja ebda degan orang lain.
saya sudah beli dan baca buku ini,
dan sungguh bikin saya ngiri, pengen bikin buku jg 🙂
oh ya ulasannya dalam, keren pak !
wah, oke juga tuh, mas, semoga keinginannya utk bikin buku sendiri bisa segera terwujud, mas.
Mungkin nama Mano nyontek dari sini yah?
Resensinya menarik… saya jadi kepingin baca bukunya secara lengkap
makasih banyak.
.-= Baca juga tulisan terbaru Seti@wan Dirgant@Ra berjudul "Experiential Learning : GURU TERBAIK (2)" =-.
walah, biasa saja kok, mas amri, hehe …. terima kasih apresiasinya.
RAIHLAH “JATI DIRI MANUSIA”.. untuk
MENGEMBALIKAN JATI DIRI BANGSA INDONESIA
Salam Cinta Damai dan Kasih Sayang ‘tuk Sahabatku terchayaaaaaank
I Love U fullllllllllllllllllllllllllllllll
.-= Baca juga tulisan terbaru KangBoed berjudul "Apalah Arti Manusia Tanpa Memiliki Kesadaran !!" =-.
i love you full too, kangbud.
Salam Cinta Damai dan Kasih Sayang ‘tuk Sahabat Sahabatku terchayaaaaaank
I Love U fullllllllllllllllllllllllllllllll
.-= Baca juga tulisan terbaru KangBoed berjudul "Apalah Arti Manusia Tanpa Memiliki Kesadaran !!" =-.
hmmm …
Mari kita renungkan bersama sama Apalah Arti Manusia Tanpa Memiliki Kesadaran !!.. sungguh tiadalah artinya jika manusia tidak memiliki kesadaran.. manusia manusia keledai yang selalu terpuruk untuk masuk dalam lubang lubang jerat keduniawian dengan senang dan gagahnya tanpa pernah memikirkan ariti hidup dan kehidupan yang sebenarnya dan sesungguhnya.. manusia manusia dengan kesadaran rendah yang merusak keseimbangan alam semesta.. sungguh menyesal diri jika kita tidak melangkah untuk meraih KESADARAN itu.. karena tanpa KESADARAN semua laku menjadi SIA SIA PERCUMA belaka..
.-= Baca juga tulisan terbaru KangBoed berjudul "Apalah Arti Manusia Tanpa Memiliki Kesadaran !!" =-.
sepakat, kangboed, hanya dengan kesadaran, manusia bisa mengembalikan jati dirinya.
Sungguh… kesadaran itu sangat…. sangat… sangat lah utama sekali di dalam kehidupan ini….
Tanpa kesadaran maka bagaimana mungkin taubat seseorang bisa diterima?
Tanpa kesadaran maka bagaimana mungkin Amal Ibadah bisa sampai kepada Allah?
Tanpa kesadaran maka manusia itu akan terombang ambing oleh kebingungan dan kegelisahan di jiwanya…….
.-= Baca juga tulisan terbaru KangBoed berjudul "Apalah Arti Manusia Tanpa Memiliki Kesadaran !!" =-.
setuju banget, kangboed.
Apalah Arti Manusia Tanpa Memiliki Kesadaran !!.. Mari Kita bersama berjalan mengupas dan sama sama meraih kesadaran.. agar kita semua menjadi pemenang sampai akhir nanti.. hidup dalam Ketenangan Jiwa.. Fitrah Diri dalam Pelukan Cinta Illahi.. senantiasa merasakan Nikmat kehadiran dan sapaan Allah yang sangat lembut meliputi setiap kehadiran kita dalam CINTA DAMAI dan KASIH SAYANG ALLAH yang MELIPUTI.. mari sahabatku semuanya jangan lalai lagi.. melangkahlah..:x:x
.-= Baca juga tulisan terbaru KangBoed berjudul "Apalah Arti Manusia Tanpa Memiliki Kesadaran !!" =-.
bedanya saya dengan Mr Sawali, tdk ngeblog sebentar saja rasanya bak setahun, tp sy setahun mangkir rasanya sehari hiks. Menarik bukunya, (bayangan dr ringkasan di atas),
.-= Baca juga tulisan terbaru wahyubmw berjudul "Ultah SMART-ku" =-.
hehe … pak wahyu bisa saja nih. bukunya memang menarik banget, pak.
kok susah comment ya, ….
.-= Baca juga tulisan terbaru wahyubmw berjudul "Ultah SMART-ku" =-.
Membahagiakan sekali, Bapak bisa mendampingi anak-anak ke kota metropolitan. Pasti mereka bahagia sekali.
Pak Sawali patut dijadikan teladan bagi guru-guru yang lain dalam keadaan rekreasipun mampu melakukan aktifitas bedah buku.
Saya tertarik untuk mengoleksi bukunya.
.-= Baca juga tulisan terbaru Puspita W berjudul "Kehilangan I" =-.
hehehe … bu pita bisa saja nih. hmm … bukunya memang menarik, bu, mangga, kalau ada waktu dicari di toko buku terdekat.
ah, nyari bukunya ah …..
.-= Baca juga tulisan terbaru yanti tukang kerupuk berjudul "Ketika Hukum Senilai Recehan!" =-.
mangga, mbak yanti. semoga segera dapat bukunya.
sering-sering bikin review ya, pak, pengen belajar bikin review juga saya 🙂
eh, atau adakah panduannya untuk membuat review?
maturnuwun sanget
.-= Baca juga tulisan terbaru goop berjudul "Gita dan Dika" =-.
widih, mas goop. mas goop kan sudah biasa me-review juga, kan? hehe …
menjadi tertebus ketidakhadiran dengan review ini, dan anak2 mendapatkan kesempatannya.
oh ya … sering dengar ulasan tentang dunia yang serba hedonis yang ditujukan pada masa sekarang, padahal hedonis pada kadarnya sendiri ada pada setiap zamannya, begitu juga dengan ironi2 kehidupan yang dikerangking dengan kata “populer” yang juga ada sebelumnya.
Membaca review ini … awal yang menarik untuk membuat penasaran.
.-= Baca juga tulisan terbaru HE. Benyamine berjudul "PUISI (16)" =-.
hehehe … iya, nih, bang ben. untungnya masih bisa menebus ketidakhadiran itu dg baca2 novelnya di perjalanan, hehe …
Sayangnya tidak gratis :d :(|)
hehehe …. konon ada yang bilang, yang serba gratis ndak selalu bisa menjadi pemicu adrenalin utk berproses kreatif, mas wempi, hehe …
mampir pak. . salam kenal n dtunggu kunjungan baliknyaa. . .:d:d:d
.-= Baca juga tulisan terbaru Astaga.com Lifestyle On The Net berjudul "Astaga.com Lifestyle On The Net Kontes SEO Astaga Berhadiah Total 30 Juta" =-.
salam kenal juga, mas. makasih kunjungannya. langsung ke tkp!
baca resensinya pak Sawali rasanya sudah cukup tanpa harus membaca bukunya… hahahahahaha… :d/
widih, jangan puas hanya sekadar membaca review-nya loh, mas mahendra, hehe …
harus dipikirkan pula pola asuh dan pola didk yang tidak mengikat tapi mendukung mental spiritual anak supaya tidak gamang mentalnya
.-= Baca juga tulisan terbaru mamah aline berjudul "Weekend bareng soulmates" =-.
hmmm …. ini review kumpulan cerpen loh, mbak, hehe …
ilang gak komennya
.-= Baca juga tulisan terbaru mamah aline berjudul "Weekend bareng soulmates" =-.
berkunjung aja pak… lama gak kesini 🙂
mangga, mas heri, matur nuwun.
Hm.. buku itu kayaknya harus dibaca juga oleh kalangan pemerintah juga.. diliat dari bahasannya pak Sawali, kayaknya cerpen-cerpen yang ada di dalma buku tersebut menggambarkan kondisi nyata yang ada di masyarakat saat ini.
mulai masalah bunuh diri sampai ngantri pengobatan alternatif..
soalnya pemerintah saat ini cuman mau ngurusi masalah gede yang ngelibatin uang gede juga… sedangkan masalah kayak bunuh diri sampai pengaruh kemiskinan terhadap kesehatan masyarakat agak kurang diperhatikan… Tapi gak tau lagi yah, itu pendapat saya sch…
btw, reviewnya mantabs pak!
.-= Baca juga tulisan terbaru nico berjudul "Baru ngerasain manfaat blogwalking dan ngeblog" =-.
saya kira ada benarnya juga, mas nico. malah ada yang bilang, teks sastra sesungguhnya bisa dijadikan sbg sumber otentik utk memperkaya sumber pengambilan kebijakan pemerintah, mas.
kayaknya menarik bukunya, di surabaya udah beredar belum ya??
.-= Baca juga tulisan terbaru Anas berjudul "Jejaring Sosial Lokal Andalan" =-.
hmm … mangga dicari, mas anas. mudah2an segera dapat bukunya.
bedah buku yang menarik pak, Kunjungan perdana dan salam hormat saya
.-= Baca juga tulisan terbaru munir ardi berjudul "Kekuatan Keikhlasan" =-.
terima kasih kunjungan dan komentarnya, mas munir.
Wah.. dari baca ulasannya saja buku ini, sepertinya sangat menarik, sarat akan konflik kehidupan sehari hari, namun bisa dijadikan sebagai bahan renungan…
begitulah, mas yulian, hehehe … kisah2nya memang menarik dijadikan bahan renungan.
wah pastinya buku menarik.. tiap hari kawan-kawan blogger semakin maju dengan kumcer serta buku2 karangan yang lain..
smoga suatu saat saya juga bisa.. hehe
.-= Baca juga tulisan terbaru azaxs berjudul "Whitehall Mailboxes" =-.
ayo, mas azaxs pasti bisa, kumpulkan saja cerita2nya, mas. kalau dah ngumpul, serahkan naskahnya ke penerbit.
wah seandainya saya juga bisa menulis apalagi fiksi seperti itu..hmmm..pasti menyenangkan….
wew… ayo dicoba dong, mas er. sampeyan pasti bisa.
Wah… ternyata Pak Sawali ke Ibu Kota. Kok nggak kekabaran, Pak?
Membaca tinjauan Pak Sawali, nampaknya kumcer Latree Manohara layak dijadikan koleksi nih.
.-= Baca juga tulisan terbaru Moh Arif Widarto berjudul "Informasi Pendaftaran Calon Siswa SMA Taruna Nusantara 2010-2011" =-.
hehehe … mau ngabari mas arif takut mengganggu, hehe … lagian juga sama anak2, mas. lain kali saya tak kabar2 dulu kalo mau ke ibukota, hehe …
sing penting aku melu komen,hehehe,…..
.-= Baca juga tulisan terbaru cah ndueso berjudul "salam sahabat/eh salan kekoncoan he..he..omongne …" =-.
walah ….
Setelah sampai di seberang, perahu yang indahpun perlu ditinggalkan. Pengarang yang sudah sampai ke seberang mungkin sudah tidak terbebani lagi aneka tata cara dan gaya bahasa.mereka lancar-lancar saja nulisnya ya[-(:)>-:d/
betul, mas love. dan saya yakin mas love sdh masuk ke tataran itu, kan?
buku yang menurut cerita diatas menarik, patut dibuat referensi
.-= Baca juga tulisan terbaru ciput mardianto berjudul "Sometimes" =-.
hmm … mangga mas ciput. referensi khususnya dalam literasi sastra, mas.
buku yang menarik nih kayaknya…..:-?
memang menarik, mas fatih. mangga dicari di toko buku, hehe …
menarik memang nihh
.-= Baca juga tulisan terbaru Hidup Untuk Berbagi berjudul "Hidup Untuk Berbagi" =-.
betul sekali, mas. mangga kalau ada waktu sempatkan utk mencarinya di toko buku, hehe ….
Wah resensi yang menarik, Pak Sawali.
Dari judulnya saya sudah bisa menebak pasti ini bukan termasuk genre konvensional. Dari postingan ini saya jadi tertarik untuk membelinya kelak ketika saya mudik ke Indonesia.
Dan yang mbikin saya cukup kaget adalah editornya Dwicipta.
Dia itu salah satu teman saya yang dulu pernah beberapa waktu diskusi santai di coffeeshop di Jogja.
Lama tak kunjung muncul (kecuali dulu ketika saya baca KOMPAS tiap hari dan menemukan namanya di sana sbagai penulis cerpen atau pengisi kolom sastra/budaya) eh lha kok saya nemu namanya di sini lagi… :))
.-= Baca juga tulisan terbaru DV berjudul "Batu Penjuru" =-.
hmmm…. ternyata mas donny malah sdh sering diskusi dan ngobrol bareng dwicipta. saya terakhir bertemu waktu ada acara ksi di kudus beberapa tahun yang lalu, mas.
bagus sekali pak, saya pikir postingan berisi suicide yang sedang ngetrend di mall-mall, ternyata review buku…..
hehehe… suicide yang itu pasti beda, mas pengendara. ini fiksi kok, hehe …
hmm..
manusia sungguh beruntung..
dgn berbagai konflik dlm hidup..
haruskah diselesaikan dgn suicide..
..
btw, 10 teman yg mendapatkan..
novel Debu Cintayana..
bisa dilihat di artasastra.com 😀
.-= Baca juga tulisan terbaru Budi Hermanto berjudul "Terima Kasih pren, inilah 10 Novel Debu Cintayana" =-.
oh, ya? alhamdulillah, setelah saya tengok, akhirnya sata termasuk 1 di antara 10 orang yang beruntung mendapatkan novel debu cintayana. matur nuwun, mas her.
salut bapak,…. memang buku gudangnya ilmu…
.-= Baca juga tulisan terbaru dameydra berjudul "Join Djarum Black Competition Vol II" =-.
setuju, mas damey, hehe … ungkapan itu akan terus berlaku sepanjang peradaban, mas guru.
terkadang kita harus memilih ya pak.. saya juga sudah membaca resensi suicide dari blog teman-teman yang lain. kumcer yang sangat menarik memang
salam kenal pak guru
hmmm … ternyata banyak juga temen blogger yang mereview-nya, ya, mbak. kumcer ini memang menarik, kok.
wah pak sawali ini ngereview buku yah….covernya bagus , isinya juga pasti okey
.-= Baca juga tulisan terbaru Miss Anna berjudul "Google Adsense oh Google Adsense" =-.
hehe …. meski cover belum tentu menggambarkan isinya, namun yang pasti isi kumcer ini memang menarik utk dibaca, mbak.
coba main-main ke blognya Si Mbak ah
nambah-nambah teman :d
.-= Baca juga tulisan terbaru tomy berjudul "KETUHANAN DALAM KISAH DEWA RUCI" =-.
hehehe … pak tomy? mangga langsung ke tkp, pak? hadir ndak pas acara peluncurannya, pak?
ya banyak jln menuju Roma pak, trims
.-= Baca juga tulisan terbaru hobby exchange berjudul "Earn Money by Shortening Your URL" =-.
sepakat banget dg makna idiom itu, mas.
Kompleksitas hidup yang tertuang dalam sebuat buku, menghadirkan realita orng-orang yang terjebak dalam riuhnya kota ya pak.
Sepertinya buku yang menarik, namun saya masih belum punya waktu
dan uanguntuk membacanya.Semoga saya diberikan kesempatan itu.
.-= Baca juga tulisan terbaru mandor tempe berjudul "Kutunggu Mataharimu" =-.
bukunya memang menarik, mas mandor. mangga, kalau memang ada waktu dan kesempatan, cari di toko buku terdekat, hehe ….
Oalah… baca blog ini yang cuma 1 halaman saja sering nggak kuwat, apalagi mbaca buku yang sampai ratusan halaman.
Tapi saya tetep salut kepada semua penulis, khususnya disini mbak Latree Manohara. Semoga dunia kepenulisan di Indonesia tetep maju.
Juga doakan saya betah baca blog, baca buku, dan baca-baca lain.
.-= Baca juga tulisan terbaru rochman berjudul "Gamelan Laptop" =-.
kekeke …. pak jai bisa saja nih.
jadi tren ya bos? apa agama kurang kuat ya?
hehehe …. mas suwung? apa hubungannya dg agama, mas? suicide-nya kah?
lho komentku kok ilang?
tapi muncul juga kok komennya? saya juga ndak tahu nih, apa penyebabnya? hehe …
Jangan berhenti menulis pak..terus semangat…
terima kasih support-nya, mas.
terus semagat pak…comment nya ko ga nampil????
jika cerpenis mereview temannya 🙂
di jakarta ga bilang-bilang pak. saya kan juga lagi di jakarta
.-= Baca juga tulisan terbaru novi cuk lanang berjudul "The Heroes and The Bonex" =-.
wow… ternyata mas novi di jakarta juga? wah, kalau tahu, pasti saya kontak.
sepertinya sangat menarik sekali isi dari buku ini, bisakah Pak Guru pinjemin sayah ? :d
selamat malam & selamat beristirahat 😀
-salam- ^_^
.-= Baca juga tulisan terbaru Hariez berjudul "Cerita Update" =-.
hehe … silakan main ke kendal, mas hariez. silakan baca sampai puas, hehe …
ternyata buku yah. saya kirsa soal suicide jumper yg lagi marak
hehehe … ini buku kumpulan cerpen, mas arham.
Ingat buku… Ingat yang mau ku pengenin.. udah ada belum pak.. hehehe..:)
.-= Baca juga tulisan terbaru Cah Sholihah berjudul "Lagi-Lagi Soal Cinta" =-.
doh, maaf banget, mbak. hingga sekarang belum juga dapat kiriman buku dari penerbit.
kalau boleh tau,kumpulan cerpen mbak Latree bercerita tentang fiksi atau pengalaman pribadi yah kira2?
.-= Baca juga tulisan terbaru pakne galuh berjudul "Tukang Panjat" =-.
hehe … fiksi kan bisa juga berasal dari pengalaman pribadi toh, pake galuh.
wah , pak sawali emang orang sibuk neh ,…..
pantesan rumah saya blom dikunjungi lagi 😀
semoga lancar pak amanah yg diberikan 😀
.-= Baca juga tulisan terbaru afwan auliyar berjudul "Keyword Research, cara jitu mendobrak trafik blog" =-.
hehe … bukannya sibuk, mas afwan. hanya sok sibuk, hehe …
wah keren neh…
.-= Baca juga tulisan terbaru barajakom berjudul "Cara Membuat Label di Blogspot" =-.
hehe … yang keren apanya, mas baraja? hehe ….
:d/ numpang baca baca yakk, makasih
.-= Baca juga tulisan terbaru sheero berjudul "Jasa Instalasi Komputer" =-.
mangga, silakan, makasih sudah menyempatkan diri utk baca2.
kumcer yang menarik, walaupun baru baca hanya dari ulasan singkat. Daya tarik yang sangat kuat karena ceritanya seputar realita hidup yang memang sangat menarik untuk diamati dan direnungi.
Cara Membuat Web
terima kasih apresiasinya, mas. mbak latree memang punya talenta besar utk menjadi seorang pengarang yang layak diperhitungkan.
Judul yang seram ya… Suicide => bunuh diri…. sangat gelap…
.-= Baca juga tulisan terbaru tengkuputeh berjudul "RISALAH SANG DURJANA BAGIAN LIMA" =-.
hehehe … mungkin karena itulah dipilih jadi judul bukunya, mas tengku.
buset manohara dah jadi penulis buku yah :d
Hi salam kenal, just blogwalking doang. main dong ke blog saya
http://blog.unsri.ac.id/kaskuserr/nais-inpo-gan/mrlist/1234/
http://blog.unsri.ac.id/kaskuserr/news/mrlist/1233/
dijamin KETAGIHAN …!!!! ^_^
salam
doh, jangan kaitkan nama latree manohara dengan si istri pangeran kelantan itu, mas. nama latree manohara sudah lebih dahulu ada sebelum kasus manohara itu mencuat ke publik, kok.
Hi salam kenal, just blogwalking doang. main dong ke blog saya
http://blog.unsri.ac.id/kaskuserr/nais-inpo-gan/mrlist/1234/
http://blog.unsri.ac.id/kaskuserr/news/mrlist/1233/
dijamin KETAGIHAN …!!!! ^_^
salam
makasih infonya.
buku yg bagus dan menarik pak….:)
begituh, mas bayu. buku ini memang menarik.
iya kayaknya keren juga bukunya
memang keren, mbak ufi. mangga, kalau ada waktu dicari.
iya bukunya kerenjuga ya pak,
Kelihatannya bukunya menarik, patut dibaca :d
.-= Baca juga tulisan terbaru SmarterDOS berjudul "Jika Aku Menjadi MENKOMINFO" =-.
“suicide” memang buku yang menarik, mas. layak utk dibaca dan dimiliki.
Dari review cerpen diatas menurut saya dapat memberikan suatu petualangan baru bagi pembacanya tentang sosok seorang ibu yang mampu memainkan 13 karakter yang berbeda dan tentu saja pembaca dibawa untuk menyelami karakter itu dengan imajinasi mereka masing-masing
.-= Baca juga tulisan terbaru Ifan Jayadi berjudul "Di Dalam Angkot" =-.
Wah numpang baca buat belajar ya mas..
mangga, silakan, matur nuwun.