Si Ratih muntah-muntah lagi. Badannya panas menyengat. Napasnya sengal. Dadanya seperti terhimpit beban yang teramat berat. Aku mulai panik. Menurut petugas puskesmas yang memeriksanya tadi pagi, si Nok yang belum genap dua tahun itu mestinya cepat-cepat kularikan ke rumah sakit. Tapi sama sekali aku tak punya keberanian. Sepeser pun duwit tak punya. Jangankan untuk berobat, sekadar untuk bisa makan pun terpaksa harus ngutang di warung Bu Mantri Darsan. Pemberian Kang Kadir, suamiku, tempo hari pun sudah ludes di perut dan mencicil sebagian utangku pada Bu Mantri.
Seandainya Kang Kadir di rumah, mungkin tak seberat ini beban yang mesti kutanggung. Setidaknya, ia bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Tapi baru dua pekan ia meninggalkan kami; aku, si Nok, dan simbok mertua yang lumpuh. Kang Kadir sendiri pun mungkin tengah bergulat mengadu nasib yang menelikungnya di kota. Dan itu berarti kepulangan Kang Kadir masih du apekan lagi seperti yang biasa ia lakukan. Pulang sebulan sekali. Aku benar-benar bingung. Pikiranku buntu.
Tangis si Ratih meledak. Aku semakin panik.
“Coba diurut punggungnya dengan brambang, Ndhuk! Masuk angin si Nok itu!” seloroh simbok mertua lirih namun terdengar jelas dari biliknya yang sumpek. Cepat-cepat punggung si Ratih kuurut dengan brambang. Tangisnya kian menjadi-jadi. Meronta-ronta. Tapi aku masih sedikit lega setelah sejurus kemudian si Ratih terdiam. Wajahnya dibalut kelelahan. Pucat. Panas badannya belum juga menurun. Kuselimuti tubuh kecil itu dengan jarik kumal yang masih basah oleh bekas muntahan. Aku ngungun di sisi dipan tua.
Benakku menerawang. Tiba-tiba saja bayangan Marno berkelebat. Terngiang jelas betapa kuatnya hasrat Marno untuk memiliki aku. Berulang-ulang, lelaki yang keranjingan judi dan suka main perempuan itu membujuk agar bersedia menjadi istrinya. Tapi berulang-ulang pula aku menolaknya. Selain karena aku sudah bertunangan dengan Kang Kadir yang kini menjadi suamiku, pada dasarnya aku memang tak suka tabiatnya. Tapi rupanya Marno sulit kuberi pengertian. Dengan berbagai macam cara ia terus berupaya menjeratku. Kekayaan orang tuanya dijadikan senjata. Saban hari, aku selalu dipameri dengan setumpuk duwit. Aku bergeming, bagiku, hidup berumah tangga tak semata-mata karena setumpuk suwit.
Gagal menjeratku, Kang Kadir yang jadi sasaran. Kang Kadir disuap agar mau melepaskan aku. Namun, Kang Kadir pun tak bisa diperalatnya. Tekad kami; aku dan Kang Kadir sudah bulat, hidup berumah tangga dengan resiko seberat apa pun. Karena usahanya selalu gagal, Marno menempuh dengan cara kekerasan. Suatu ketika, terjadilah pertengkaran hebat dengan Kang Kadir. Kang Kadir pu tak mau mengalah hingga akhirnya terjadi perkelahian seru. Kang Kadir babak-belur dihajar oleh Marno dan kawan-kawannya. Untunglah para penduduk kampung berhasil melerainya.
Sejak peristiwa perkelahian itu, Marno tak pernah lagi menghalangi kami. Bahkan, setelah kami kawin, Marno pun menikah dengan Sumi, anak Bu Mantri Darsan yang baru saja lulus dari SMA. Kehidupan rumah tangga kami pun berlangsung tenteram dan bahagia. Tapi sayang, rumah tanggaku mulai berkabut setelah ayah mertuaku meninggal akibat penyakit paru-paru kronis. Simbok mertuaku mulai sakit-sakitan, bahkan kedua kakinya lumpuh. Beban yang harus dipikul Kang Kadir pun semakin berat. Selain harus meafkahi kami; aku dan si Nok yang baru saja lahir, Kang Kadir disibukkan dengan upaya mencari cara penyembuhan simbok mertua. Berobat lewat rumah sakit berulang-ulang sudah dilakukan, bahkan lewat dukun pun ditempuhnya. Tak mengherankan jika beberapa petak sawah dan barang-barang berharga ikut ludes. Namun, kelumpuhan yang diderita simbok mertua tak kunjung sembuh. Bahkan, hingga si Nok berumur hampir dua tahun, penyakit lumpuh itu tetap bersarang di tubuh simbok mertua.
Hatiku semakin pilu. Untuk menutup kebutuhan sehari-hari, Kang Kadir merantau ke kota. Sebulan sekali ia pulang dengan penghasilan yang tidak menentu. Hidup kami pun senin-kemis. Jika pemberian Kang Kadir habis, aku terpaksa ngutang di warung Bu Mantri Darsan meski harus menghadapi serentetan sindirian dan olok-olok.
Kutatap wajah si Ratih yang pucat. Ulu hatiku serasa dihantam godam. Perih. Di biliknya yang sumpek, mungkin simbok mertua tengah merenungi nasibnya yang malang. Hidupnya hanya tinggal menunggu jemputan maut. Dan boleh jadi, simbok mertua telah meyakini bahwa itulah yang sudah jadi garis hidupnya. Ia hanya bisa pasrah. Sedikit pun tak pernah terdengar keluhan. Sementara itu, malam pun semakin larut. Sepi. Sesekali, terdengar desah dan batuk si Ratih yang berat. Di luar, angin terdengar menampar-nampar pepohonan.
Aku benar-benar dihimpit beban nasib yang demikian berat. Aku mulai menyadari betapa pentingnya duwit di zaman seperti sekarang ini. Dengan duwit, tentu nasib di Ratih tak akan demikian tersiksa. Setidak-tidaknya, penyakitnya bisa diobati secepatnay di rumah sakit. Aku mendesah berulang-ulang. Benakku penuh dengan setumpuk pertanyaan yang sulit kujawab. Tiba-tiba saja tangis Ratih membuncah sepi. Lengkingannya seakan menggema ke angkasa. Hatiku semakin pedih. Buru-buru ia kugendong sekadar untuk bisa meredakan tangisnya. Namun, penyakit yang dideritanya belum juga mau lepas dari tubuhnya yang semakin kurus. Badannya masih saja panas menyengat. Napasnya sengal. Batuk pun terus memberondong tenggorokannya, dan setelah itu ia mutah-muntah lagi.
***
Aku tersentak ketika Marno datang ke rumahku secara tiba-tiba. Motor bebek terbarunya nampak terparkir di halaman rumahku yang kelewat sempit. Dadaku berdebar-debar. Benakku hanya bisa menduga-duga maksud kedatangannya. Barangkali saja ia hendak membangkitkan luka lamanya. Ia hendak menjeratku kembali. Atau boleh jadi ia hanya sekadar iseng?
“Selamat pagi, Lastri! Kok sepi sekali, di mana Kadir?” tanya Marno sembari duduk di kursi tua yang reot. Aku tertunduk. Rasa muak menyesak di dadaku. “Mungkin kamu masih sakit hati dengan saya. Saya memang brengsek. Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk minta maaf!” sambungnya. Kata-katanya kurasakan seperti berondongan senapan di telingaku. Aku bergeming. Si Ratih yang kugendong menangis lagi. Serak.
“Anakmu kenapa Lastri? Sakit? Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit?” tanya Marno. Sungguh, pertanyaan itu jelas-jelas sebuah penghinaan. Darahku berdesir. Wajahku memerah. Aku betul-betul merasa tersinggung. Kutatap wajah Marno dengan penuh kebencian.
“Pergi! Pergi sekarang juga dari rumahku!” bentakku taku kuat menahan amarah. Marno tersenyum. Aku semakin merasa terhina.
“Lastri, anakmu butuh pengobatan secepatnya! Tidakkah kamu bisa merasakan penderitaannya?”
“Tidak! Lebih baik kamu saja yang segera kabur dari sini!”
“Lastri, anak adalah amanat Tuhan. Kamu harus bersyukur dan harus bisa merawatnya.
Sedangkan aku? Lima tahun hidup bersama Sumi belum juga dikaruniai anak!” Marno mendekatiku. Tangannya mengusap lembut wajah Ratih yang pucat. “Untuk menebus kesalahanku di masa lalu, biarlah aku yang membawa anakmu ke rumah sakit. Masalah biaya aku yang nanggung!”
Aku seperti terlempar ke sebuah gua yang singup. Hatiku menangis. Dadaku tiba-tiba saja terasa sesak. Aku tak tahu lagi bagaimana harus menghadapi Marno. Namun, melihat kesungguhan Marno, aku tak mampu berbuat apa-apa ketika ia mendesakku untuk membawa Ratih ke rumah sakit.
Aneh! Selama menginap di rumah sakit, Marno pun rutin menjenguk Ratih. Dan yang tak bisa kupahami, ia selalu membawa serta Sumi, istrinya. Marno memang benar-benar telah berubah, pikirku. Kesehatan si Ratih berangsur-angsur pulih. Aku benar-benar bersyukur. Marno benar-benar menepati janjinya. Semua biaya rumah sakit ditanggungnya.
Si Ratih benar-benar telah sehat. Ia mulai bermain-main dengan dunianya. Sejak itu, pandanganku terhadap Marno pu berubah. Di mataku ia telah menjadi dewa penolong. Tanpa dia, aku tidak tahu bagaimana nasib si Ratih selanjutnya. Kekhawatiranku tentang niat buruk di balik pertolongannya pun tak terbukti.
***
Cuaca cerah. Matahari telah sepenggalah. Kabut di rumahku sedikit tersibak dengan sembuhnya Ratih. Hatiku senang melihat si Nok sudah menemukan kembali kebiasaannya. Riuh. Tiba-tiba saja Marno datang. Kali ini ia sendirian. Aku menyambutnya ramah. Kesan kebencian sudah sirna. Seperti biasa, ia langsung duduk di kursi tua yang reot. Aku berulang kali mengucapkan terima kasih. Marno tersipu.
“Itu semata-mata kulakukan demi anakmu, si Ratih. Sekaligus menebus kesalahanku. Aku senang jika kamu menerimanya!” balas Marno tenang.
Dari jauh terdengar deru kendaraan membelah perkampungan. Aku terhenyak ketika motor itu dengan cepat menuju ke rumahku. Kang Kadir. Ia pulang dengan tas yang memberat di pundaknya. Setelah membayar tukang ojek, Kang Kadir bergegas masuk rumah. Aku menyambutnya. Kang Kadir tersenyum. Tapi mendadak wajahnya berubah liar ketika bola matanya beradu dengan wajah Marno. Kang Kadir tampak menegang. Wajahnya berpeluh. Rambutnya masih acak-acakan.
Marno tersentak ketika tiba-tiba saja kedua tangan Kang Kadir mencengkeram kuat-kuat krah baju Marno. Marno gelagapan.
“Bangsat! Rupanya belum kapok juga mengganggu istri orang!” benatk Kang Kadir sembari mendorong cengkeramannya. Marno terjengkang. Tenggorokanku tercekat. Ingin segera aku menjelaskan dan memberi pengertian kepada suamiku yang barusan pulang dari kota itu. Tapi gerakan Kang Kadir kelewat cepat. Tangannya memukul perut dan wajah Marno. Kaki kanannya dengan cekatan menendang tubuh Marno hingga terpelanting ke sana kemari. Dalam sekejap saja, tubuh Marno babak-belur. Tubuhnya loyo. Terkapar di lantai. Aku menjerit-jerit. Orang-orang kampung segera tumpah ke rumahku. Mataku nanar. Batinku terkoyak menyaksikan kebringasan Kang Kadir. ***
(Wawasan, 3 Agustus 1997)

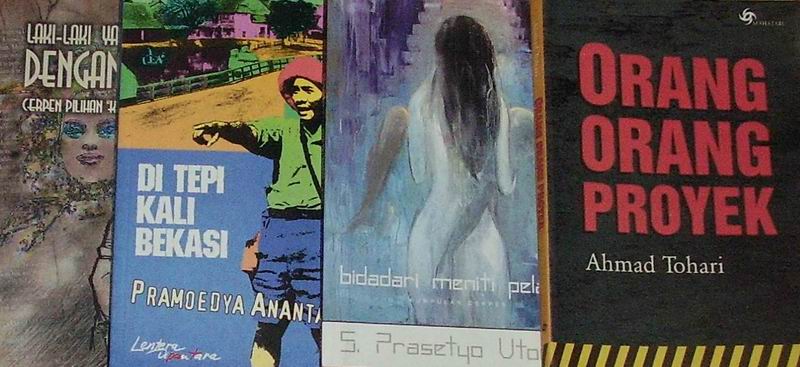
1 Comment