Nada tangis pilu memecah perkampungan, mengiris atap-atap rumah, mengusik mimpi-mimpi yang membadai di layar bawah sadar para penduduk. Fajar baru saja menggeliat dari kepungan malam yang busuk. Sambil mengucak-ucak pelupuk mata, beberapa penduduk berjingkat dari pembaringan, menerobos pintu, menyibak kabut dingin.
“Ada yang meninggal, ya, Kang?” tanya seseorang.
“Mungkin!” sahut yang lain.
“Kira-kira siapa yang meninggal, ya, Kang?”
“Mana aku tahu? Tapi kalau ndak salah tangisan itu dari rumah Kang Panut!”
“Tapi setahu saya keluarga Kang Panut sehat-sehat saja, kok!”
“Yah, semoga tidak ada apa-apa!”
Mereka terus berjalan menyusuri jalan desa yang dingin dan berkabut. Tergesa-gesa. Suara tangis makin menyayat-nyayat. Para penduduk makin tak sabar. Ketika tiba di rumah Kang Panut, mereka menyaksikan kesibukan yang berlangsung di gubug reot berdinding bambu itu.
“Urut pergelangan kakinya!” seru seseorang.
“Bikinkan kopi, cepat!”
“Tekan jempol kakinya!”
Suara penduduk kampung yang riuh berbaur dengan bau mulut, suara batuk, suara tangis, suara kokok ayam. Di kejauhan sana suara azan subuh menggema, menampar dinding bukit, menggoyang lembah hantu dan demit, menggetarkan kaki langit. Di atas pembaringan, Kang Panut tergolek tak berdaya. Bola matanya mendelik dahsyat. Wajahnya pasi, kehilangan cahaya kehidupan. Napasnya berat dan sesak. Kerongkongan dan rongga dadanya seperti tersumbat beban yang mahaberat. Beberapa penduduk sibuk mengurusnya. Namun, agaknya Tuhan telah berkehendak lain. Lelaki kurus itu tiba-tiba meronta dahsyat, lalu diam, tak berkutik. Sekujur tubuhnya kaku dan dingin. Mati. Seorang perempuan kurus memekik histeris; roboh dan tersungkur ke lantai. Kabut duka bergulung-gulung menyelimuti gubug reot itu.
Tak seorang pun menduga, Kang Panut bakal meninggal secepat itu. Kemarin, para penduduk masih sempat menyaksikan lelaki kurus bermata juling itu bekerja sebagai tukang masak air di rumah Pak Lurah Kimpul yang sedang punya hajat mantu. Dengan celana kolor hitam dan kaos oblong lusuh, Kang Panut bergelut dengan api dan asap dapur. Memasak air untuk suguhan para tamu. Wajahnya tampak lelah. Namun, Kang Panut tak menghiraukan. Dia terus bekerja sampai hajat usai.
Agaknya Kang Panut menikmati betul pekerjaannya itu. Hanya dengan upah lima ribu rupiah, dia sambut tawaran setiap penduduk yang membutuhkan tenaganya dengan senang hati. Yu Ginem, isterinya pun tak pernah berontak. Dari dalam gubugnya yang reot itu hampir tak pernah terdengar percek-cokan. Hanya sesekali terdengar tangis kedua anaknya yang saling berebut makanan atau nasi kenduri dari tetangga. Selebihnya, gubug reot itu senantiasa sunyi, tersisih di sudut perkampungan yang tak pernah terjamah suara radio atau televisi. Jika malam tiba, dari balik gubug itu menggema suara jangkrik atau gangsir yang bersembunyi di sela-sela gundukan cacing tanah yang lembab dan kotor.
***
Berita kematian Kang Panut bagaikan terbawa angin, menyebar dengan cepat ke seantero desa. Para penduduk berdatangan secara bergelombang. Maklumlah. Hampir semua penduduk desa dari ujung barat hingga ujung timur mengenalnya. Dia dianggap telah berjasa menghidupkan hajat banyak orang. Seandainya tidak ada Kang Panut, pasti akan sering terjadi keributan. Para tamu yang hadir merasa tidak dihargai lantaran tak disuguhi minuman. Kasak-kusuk dengan mudah dan cepat berkecamuk di setiap kepala. Memang hanya sekadar minuman. Namun, bisa menjadi persoalan besar lantaran menyangkut harga diri dan kehormatan.
Para pelayat membludak. Gubug reot itu seolah-olah mau ambruk; tak kuasa menampung pelayat yang berjejal-jelal. Sebagian yang lain menyingkir ke emper rumah-rumah tetangga. Pak Lurah Kimpul pun menyempatkan hadir. Bola matanya berkaca-kaca. Entah, pikiran apa yang tengah berkecamuk di rongga kepalanya.
“Huh! Dasar koruptor! Untuk apa ikut-ikutan layat?” gerutu seorang pemuda di tengah kerumunan pelayat yang berjubel.
“Hus! Jangan keras-keras! Ini bukan saatnya mengobral umpatan! Ndak baik!”
“Alah! Memang takut?”
“Ini bukan soal takut atau tidak takut, tapi soal kepantasan! Pantaskah kita mengumpat-umpat di tengah suasana duka seperti ini?”
“Oh, Sampean ingin membela lurah yang jelas-jelas menilap tanah bandha desa itu, hem?”
Suasana tiba-tiba tegang. Para pelayat saling bertatapan. Orang-orang yang semula menunduk takzim di sekeliling jasat Kang Panut terusik; bergegas keluar gubug dengan kepala diserbu tanda tanya.
“Hei! Jangan seenaknya menuduh orang, ya?” Plak! Sebuah bogem mentah meluncur. Terjadi keributan. Saling pukul. Para pelayat berebutan melerai. Pak Lurah Kimpul menyibak kerumunan, mengucak-ucak bola mata di balik kaca mata minusnya yang tebal. Jidatnya berkilat-kilat ditimpa cahaya matahari.
“Kalian ini gimana toh? Pantaskah ribut-ribut dalam suasana seperti ini? Bukannya mendoakan Kang Panut, tapi malah bikin keonaran. Dasar!” sergah Pak Lurah Kimpul dengan wajah memerah seperti kepiting rebus. Para pelayat kembali saling bertatapan.
“Hei, Pak Lurah! Apa hak Sampean melarang-larang orang! Jangan sok menasihati! Berkacalah Sampean!” sahut pemuda yang tadi kena bogem mentah dengan nada gemetaran. Jari-jarinya mengusap darah yang menetes dari belahan bibirnya yang pecah. Pak Lurah Kimpul terkejut. Bola matanya membelalak. Para pelayat kembali bertatapan untuk ke sekian kalinya, saling berbisik. Suasana berubah riuh seperti kerumunan lebah mencari sarang.
“Edan! Sinthing! Gendheng! Berani-beraninya ngomong seperti itu di depan Pak Lurah?” Seorang lelaki tua berikat kepala hitam menyeruak kerumunan dan mencengkeram krah baju si pemuda dengan kekuatan penuh, lantas disentakkan dengan keras. Si pemuda terjengkang.
“Sampean semua yang gendheng! Sudah kena tipu sama si Lurah brengsek itu!” sahut si pemuda dengan tubuh sempoyongan. Telunjuknya menuding wajah lelaki tua berikat kepala hitam dan wajah Pak Lurah Kimpul. Lantas, beranjak menjauhi kerumunan. Darah lelaki tua berikat kepala hitam berdesir. Rongga dadanya serasa diserbu puluhan kalajengking. Perih dan nyeri. Bola mata Pak Lurah Kimpul berkeriyap dari balik kaca mata minus tebalnya. Jantungnya bergetar hebat. Keringat meluncur deras di dahinya. Berkilat-kilat. Ulu hatinya serasa dihantam godam bertubi-tubi. Cahaya matahari seolah berubah bagaikan kilatan pedang yang siap merajam tubuhnya. Baru kali ini dia diperlakukan sekasar itu oleh warganya sendiri. Dia tidak tahu harus berbuat apa menghadapi pemuda sundal itu.
“Sudahlah, Pak Lurah! Anggap saja dia orang gila. Buat apa diurusi? Sekarang, mari segera kita urus jenasah Kang Panut!” rajuk lelaki tua berikat kepala hitam sambil tersenyum. Hambar. Pak Lurah Kimpul termangu. Pikirannya menerawang entah ke mana.
Sementara itu, para pelayat juga tak habis pikir dengan sikap si pemuda yang dianggap keterlaluan. Dalam sejarah desa di bibir hutan jati itu, baru kali ini ada seorang pemuda yang demikian nekat dan berani mengumbar kata-kata kasar di depan hidung seorang pemimpin.
Tanpa tahu sebab yang pasti, dari balik gubug duka tiba-tiba terdengar suara gaduh. Para pelayat berlarian. Berjejal-jejal.
“Kang Panut hidup lagi!” teriak seorang penduduk mengabarkan.
“Ha? Hidup lagi?” Mulut para pelayat menganga.
“Ah, tidak mungkin!”
“Lihat saja sendiri!” Para pelayat makin tak sabar.
Bagai tersihir, para pelayat terpaku menyaksikan Kang Panut duduk bersila di atas meja. Mulutnya menyeringai, menyemburkan hawa busuk. Tampak deretan giginya yang kuning dan kotor. Orang-orang sibuk menutup lubang hidung.
“Kang? Sampean hidup lagi, Kang?” tanya Yu Ginem sambil merangkul Kang Panut. Sepasang mata perempuan kurus itu berkaca-kaca seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kang Panut tak menjawab. Mulutnya terus menyeringai, menyemburkan hawa busuk. Namun, di rongga hidung Yu Ginem bagaikan aroma bunga dari sorga. “Puji syukur Ya Allah, suamiku hidup kembali!” lanjutnya sembari membungkus tubuh suaminya dengan sarung dan kaos oblong lusuh. Yu Ginem serasa bermimpi. Tubuhnya gemetar saking senangnya. Para pelayat masih termangu sembari menutup hidung rapat-rapat.
“Nem, ini anugerah dari Sing Nggawe Urip. Kamu harus bersyukur, suamimu telah kembali! Mungkin belum saatnya suamimu menghadap Gusti Allah!” kata lelaki tua berikat kepala hitam sambil mendekati Yu Ginem dan Kang Panut. Pak Lurah membuntutinya sambil menutup hidung rapat-rapat.
“Ya, Mbah!” jawab Yu Ginem sambil mengangguk-angguk.
“Nut, Panut!” sapa lelaki berikat kepala hitam. “Kamu masih mengenalku, toh?” Tak ada reaksi. Kang Panut hanya menyeringai. Hawa busuk menyembur-nyembur. Perut Pak Lurah tiba-tiba terasa mual seperti digerayangi ratusan cacing pita. Dan dia tak kuat lagi menahan isi perut yang terus menyodok-nyodok kerongkongannya. Lelaki tambun itu muntah-muntah. Para pelayat berpandangan.
“Pak Lurah sakit?” tanya lelaki tua berikat kepala hitam.
“Iya, Mbah! Maaf, aku pulang dulu, ya?”
“Iya, mangga! Sebaiknya begitu!”
Terdengar deru kendaraan memecah perkampungan. Mata para penduduk mengikuti laju Pak Lurah Kimpul hingga hilang di tikungan.
“Para sedulur!” kata lelaki tua berikat kepala hitam sambil berdiri di samping Kang Panut yang tak henti-hentinya menyeringai. Yu Ginem tampak menyisir rambut Kang Panut yang acak-acakan dan berbau. “Kita sudah sama-sama melihat, Panut dalam keadaan segar-bugar. Gusti Allah masih menghendaki dia bersama kita! Nah, sekarang, anggap tidak pernah terjadi apa-apa! Para sedulur boleh pulang!” Para penduduk berbisik-bisik. Riuh. Sambil menutup hidung, mereka berdesakan meninggalkan gubug reot itu.
***
Kabar hidupnya kembali Kang Panut dengan cepat tersebar ke desa-desa tetangga, meluas ke kecamatan, kabupaten, bahkan hingga ke kota-kota terdekat. Para wartawan media cetak dan elektronik saling berlomba meliput peristiwa menghebohkan itu. Orang-orang kesehatan merasa tertantang untuk melakukan riset khusus. Rombongan orang dari berbagai kalangan terusik untuk membuktikan kebenaran cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Desa di bibir hutan jati yang biasanya sunyi itu pun mendadak ramai dan sibuk.
Para wartawan, orang-orang kesehatan, dan mereka yang berdatangan dari berbagai kota ingin sekali mendengar penuturan langsung dari Kang Panut. Apa sebenarnya yang dia alami ketika berada dalam alam kematian. Namun, sia-sia. Kang Panut hanya bisa menyeringai, menyemburkan hawa busuk. Tak sepatah kata pun meluncur dari bibirnya yang selalu dikerumuni lalat dan serangga. Mereka yang semula penasaran tiba-tiba merasa jijik dan takut.
Waktu terus berlalu. Kehadiran Kang Panut tiba-tiba menjadi masalah besar. Setiap malam, kabarnya dia suka keluyuran, mendatangi rumah penduduk secara tak terduga, menyeringai, meninggalkan hawa busuk. Pernah suatu malam, Kang Panut mendatangi rumah penduduk yang sedang menggelar pesta hajat mantu. Di atas panggung, para biduan dangdut sedang hangat-hangatnya menghibur para penonton. Tiba-tiba tercium bau busuk. Makin lama makin menusuk-nusuk hidung. Tanpa diduga, Kang Panut sudah berada di depan tungku perapian seperti yang sering dia lakukan sebelum mati suri. Keruan saja, para penonton bubar. Rombongan pemain musik dan biduannya kabur menyelamatkan diri. Tuan rumah pingsan.
Konon, pada siang hari Kang Panut selalu mendekam di dalam gubug reotnya. Ada yang bilang, dia tak sekadar tertidur, tetapi benar-benar mati. Anehnya, pada malam hari dia kembali beraksi; datang ke rumah-rumah penduduk secara tiba-tiba. Desa seperti diselubungi bau mayat yang amat busuk. Para penduduk benar-benar tersiksa.
“Kita harus ambil tindakan secepatnya, Pak Lurah!” kata lelaki tua berikat kepala hitam di rumah Pak Lurah Kimpul yang besar dan megah. Para penduduk yang mendampinginya mengangguk-angguk. “Kalau tidak, desa kita bakalan dikucilkan desa-desa tetangga!”
“Lalu, apa rencana Sampean?”
“Kita singkirkan saja dia!”
“Caranya?”
“Serahkan saja kepada saya dan anak-anak!”
“Baik, aku setuju!”
Maka, keesokan harinya, di bawah komando lelaki tua berikat kepala hitam, para penduduk dengan wajah beringas berbondong-bondong menggrebeg gubug Kang Panut. Namun, belum sempat rencana penyingkiran Kang Panut terwujud, seorang pemuda menghalang-halanginya.
“Keliru besar kalau kalian hendak menyingkirkan Kang Panut!” kata si pemuda berkacak pinggang.
“Hei, pemuda keparat! Menyingkirlah sebelum pedang-pedang itu membabat lehermu!” sergah lelaki tua berikat kepala hitam dengan gusar.
“Tunggu dulu, Pak Tua! Sebenarnya yang lebih pantas disingkirkan itu Pak Lurah Kimpul yang jelas-jelas menilap tanah bandha desa! Bukan Kang Panut yang tidak bersalah! Tubuh
Kang Panut memang busuk, tapi mental Lurah Kimpul jauh lebih busuk!”
“Anak-anak, habisi saja dia!” komando lelaki tua berikat kepala hitam. Namun, tak ada reaksi. Para penduduk tiba-tiba tersungkur seperti daun-daun berguguran. Dari dalam gubug reot, tiba-tiba menyembur hawa busuk yang jauh lebih dahsyat; menggetarkan seisi desa. (72)
Kendal, September 2004
(Suara Merdeka, 3 Oktober 2004)

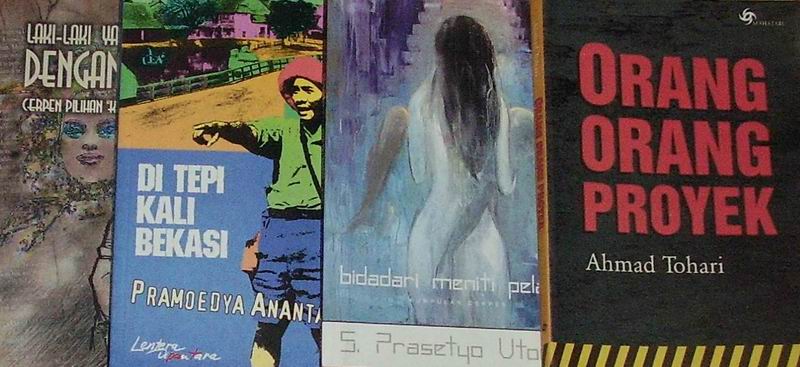
1 Comment