Warni tercenung di kamarnya. Dadanya tiba-tiba sesak. Benaknya jatuh ke tempat yang jauh. Ia rindu Emak, Bapak, dan adik lelaki satu-satunya di tanah Jawa, yang sudah hampir sepuluh tahun ditinggalkannya. Kenekadan Warni untuk menerima tugas sebagai guru di luar Jawa seakan bebar-benar telah memutuskan hubungan darah dengan keluarganya. Ia sudah berkali-kali mencoba mengirim surat ke Jawa, tapi belum pernah sekali pun mendapatkan balasan. Warni tidak tahu, apakah surat yang dikirim memang tidak pernah sampai ke alamat yang dituju atau surat itu sampai ke tangan keluarganya, tapi sengaja tidak dibalas, yang bisa diartikan ia sudah tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga.
“Kamu hanya perempuan, Warni. Buat apa jauh-jauh meninggalkan kampung halaman hanya untuk memburu duit? Tanpa harus bekerja pun ayah sanggup menanggung hidupmu, bahkan sampai kelak kamu hidup berumah tangga!” kata-kata ayahnya menari-nari di lorong ingatannya.
Ayah memang Warni tergolong orang kaya yang terpandang di kampung. Sawahnya berpetak-petak. Rumahnya paling besar dan megah. Sebagai seorang mantan kepala desa, ayah Warni begitu dihormati para penduduk. Namun, Warni tidak sepenuhnya setuju dengan sebagian sikap yang ditunjukkan oleh ayahnyayang dianggap tidak adil dalam memperlakukan dirinya. Dalam soal jodoh, misalnya, ayahnya bersikap otoriter. Warni tidak diberi kesempatan untuk memilih. Oleh ayahnya, Warni hendak dijodohkan dengan Joko, putra Pak Mantri Darpan. Tapi, Warni tidak suka dengan Joko yang pemalas dan congak, sering membangga-banggakan kekayaan orang tuanya. Oleh sebab itu, ketika ia memperoleh nota tugas sebagai guru dan ditempatkan di luar Jawa, Warni amat senang. Paling tidak, hal itu bisa dijadikan dalih untuk menghindari Joko.
“Maaf, Ayah! Soal tugas adalah soal tanggung jawab. Bukan perkara lelaki atau perempuan! Lagi pula kenapa, sih, Ayah masih saja membedakan perempuan dan lelaki. Lantas bedanya dimana?” berontak Warni.
“Warni! Apa pun alasanmu, perempuan itu dalam kehidupan rumah tangga kelak tetap di bawah lelaki. Dan ingat, secara moral kamu sudah punya ikatan dengan Joko, putra Pak Mantri itu!”
“Itulah yang membuat saya tidak setuju! Di zaman yang sudah modern ini, Ayah masih saja memaksakan jodoh. Kalau cocok, sih, enggak masalah. Tapi kalau enggak, apa ada jaminan aku bisa hidup bahagia?” berondong Warni.
“Sudah, aku tidak mau berdebat. Sekarang tinggal pilih, tetap nekad atau mengikuti kemauan Bapak!”
Dua buah pilihan yang sama-sama sulit bagi Warni. Kalau harus mengikuti kemauan ayahnya, itu berarti ia menolak panggilan hidupnya sebagai seorang guru dan harus siap hidup berumah tangga dengan Joko yang tidak dicintainya. Itu sama saja ia telah ikut mengembangkan budaya patriarki yang selama ini ditentangnya. Warni memang bukan tipe feminis, tapi ia amat tidak sependapat kalau kaum perempuan selalu dimitoskan sebagai kanca wingking, yang hanya diserahi tugas mengurus dapur, sumur, dan kasur. Namun, jika ia tidak mengikuti keinginan ayahnya, itu sama artinya telah melempar telur busuk ke wajah ayahnya yang begitu dihormati oleh orang-orang di kampung.
Beberapa hari lamanya, warni hanya ngendon di kamar. Ada segumpal mendung yang menggelayuti pikirannya. Sulit mengambil keputusan. Apalagi Ayah, Emak, dan adiknya selalu memasang wajah cemberut yang agaknya sudah sulit diajak kompromi. Namun, nota tugas yang ada dalam genggaman tangannya seperti sudah mengisyaratkan kalau ia harus secepatnya menunaikan tugas suci itu. Dalam kondisi seperti itu hanya pamannya, Om rajimo yang cukup toleran, dapat memahami keinginannya.
“Warni, kalau itu sudah menjadi keyakinanmu, berangkatlah. Om merestuimu. Om hanya berpesan, hati-hati membawa diri di kampung orang. Apalagi disana nanti tak ada sanak saudara,” kata pamannya lembut dan penuh pengertian. Kata-kata pamannya seperti mampu menyibak mendung yang bergelayut di benaknya, memantapkan langkahnya untuk segera menunaikan panggilan nuraninya, menjadi seorang pendidik di daerah yang jauh.
Akhirnya,Warni menetapkan pilihan menjadi seorang guru. Ketika hendak pamitan dengan keluarganya, ia sudah tak sanggup berkata-kata. Semua perasaannya ditumpahkan lewat surat yang dititipkan kepada Om Ramijo untuk disampaikan pada ayahnya. Dalam surat itu, Warni dengan gamblang menjelaskan bahwa kepergiannya bukan dimaksudkan menentang kehendak orang tua. Namun, semata-mata memenuhi panggilan suci sebagai seorang pendidik yang mesti di jalaninya. Selain itu, Warni dengan tegas memohon pengertian ayahnya agar tidak diskriminatif. Sudah saatnya kaum perempuan diberi hak yang sama dengan kaum lelaki. Bebas menentukan pilihan hidup sesuai dengan fitrah dan hati nuraninya.
Warni tidak tahu bagaimana reaksi ayahnya setelah membaca surat itu. Ia hanya tahu, saat ia dilepas ayahnya dengan wajah dingin dan sorot mata memancarkan amarah. Beruntung, Warni masih merasakan sikap arif dan kelembutan dari emaknya. Meski tidak setuju atas kepergiannya ke luar Jawa, Warni masih merasakan sisa-sisa perhatian dan kasih sayang di rongga hati emaknya. Dipeluknya erat-erat tubuh emaknya. Desah napas dan getaran hati mereka menyatu dalam keharuan. Warni serasa tak sanggup menahan arus air mata yang deras menjebol bendungan pelupuk matanya. Demikian juga ketika berpamitan dengan Totok, adiknya. Kedua bola mata adiknya itu tampak berkaca-kaca. Terasa amat berat melepas kepergiannya. Akhirnya, Warni benar-benar terbang ke daerah yang jauh, tempat yang diharapkan dapat menyematkan pengabdiannya untuk kepentingan sesama.
***
Di tempat tugasnya, Warni diterima dengan ramah dan sambutan hangat dari kepala sekolah dan rekan-rekan gurunya yang sudah lama bertugas. Rumah dinas pun sudah disediakan, berada di kompleks sebuah gedung SLTP yang tampak kokoh dan megah.
Sebagian beras, rekan-rekan gurunya adalah kaum pendatang. Dari berita yang ia dengar, penduduk asli daerah itu masih terbilang kolot. Kehidupan mereka masih amat tergantung pada alam. Berladang dan berburu merupakan mata pencaharian utama mereka. Memang ada beberapa perkebunan kopi yang menghampar luas, tapi itu pun dikuasai oleh para pemilik modal luar. Kesadaran penduduk asli akan pentingnya pendidikan tampaknya belum tumbuh. Anak-anak mereka masih enggan duduk di bangku sekolah. Sejak kecil, anak-anak sudah diperkenalkan dengan pola hidup sederhana oleh orang tua mereka masing-masing. Magang di lahan dan di hutan, setelah besar menikah, lantas membangun permukiman liar di sekitar hutan. Tampaknya, mereka belum bisa hidup menyatu dengan kaum pendatang. Mereka lebih suka hidup di pinggir-pinggir hutan, menyatu dengan alam. Hanya sebagian kecil penduduk asli yang mau hidup membaur dengan kaum pendatang,terutama mereka yang bekerja sebagai pegawai pemerintah.
Waktu terus berlalu. Pembawaannya yang lincah dan sikapnya yang luwes membuat Warni mudah diterima dalam pergaulan. Tak ada hambatan yang ia rasakan selama bertugas. Semuanya berjalan lancar. Hanya terkadang ia harus berhadapan dengan siswanya yang tergolong nakal.
Naluri sebagai pendidik membikin Warni sering gelisah melihat anak-anak penduduk asli yang nyaris tak pernah tersentuh kemajuan. Hidup mereka seperti tersekap dalam lorong yang gelap dan sunyi. Terisolir. Warni berkeinginan membuka mata hati mereka akan pentingnya pendidikan. Ia ingin mengajari mereka baca tulis dan menghitung. Keinginan itu ternyata tak disetujui Pak Harahap, kepala sekolah. Menurutnya terlalu riskan kalau itu harus dilakukan. Apalagi, mereka belum bisa hidup menyatu dengan para penduduk yang lain. Bisa-bisa timbul kesalahpahaman. Namun, hasrat Warni agaknya sulit dibendung. Gagal mengajak Pak Harahap bekerja sama, Warni bergegas menemui Pak Matilda, camat setempat yang sudah ia kenal baik. Oleh Pak Matilda, gagasan Warni disambut dengan baik.
Sebenarnya, jarak antara rumah dinas Warni dengan permukiman penduduk tidak terlalu jauh. Hanya dipisahkan sebuah bukit kecil setelah melintasi sebuah hamparan kebun kopi yang agak luas. Namun, lantaran tidak ada jalinan komunikasi, jarak yang dekat itu terasa jauh. Oleh Pak Matilda, Warni diperkenalkan kepada para penduduk. Ia tak tahu persis bahasa yang mereka ucapkan. Warni hanya bersikap seramah mungkin dan selalu tersenyum. Para penduduk yang berkumpul tampak mengangguk-angguk. Terasa benar Pak Matilda berhasil berkomunikasi dengan mereka. Sementara, itu puluhan anak kecil sibuk dengan dunianya, bermain pedang-pedangan. Riuh.
Agak merinding juga menatap wajah-wajah penduduk asli yang tampak dingin dan acuh melihat kehadiran dirinya. Namun, Pak Matilda sering menghiburnya. Konon, hal itu sudah menjadi ciri khas penduduk setempat dalam menyambut kehadiran orang asing. Pak Matilda terus memberikan dorongan. Lama-lama, Warni terbiasa bergaul dengan para penduduk, hingga akhirnya ia berhasil mengajak anak-anak belajar membaca, menulis, dan berhitung. Warni betul-betul menikmati misinya itu di sela-sela tugas utamanya sebagai guru di sebuah SLTP. Para penduduk mulai bisa menerima kehadirannya.
Misi pendidikan Warni ternyata membawa hikmah tersendiri. Entah bagaimana alur ceritanya, tiba-tiba saja warni terpikat oleh kehadiran Leode, seorang pendatang yang sukses sebagai pengusaha perkebunan kopi. Orangnya masih muda, tampan, dan berkulit bersih. Namun, bukan semata-mata itu yang membikin hati Warni terpikat, melainkan perhatian Leode yang cukup besar untuk mengentaskan penduduk asli dari keterbelakangan. Dengan kekayaannya, Leode sering memberikan bantuan kepada mereka. Bahkan, pemuda itu bersedia membangun sebuah gedung sekolah di tengah-tengah pemukiman para penduduk. Hati Warni semakin terpikat. Oleh sebab itu, Warni tak kuasa menolak ketika Laode meminang dirinya sebagai pendamping hidup.
***
Tanpa terasa,sudah sembilan tahun Warni meninggalkan kampung halamannya. Kini, ia sudah dikaruniai dua anak yang sehat, hasil perkawinannya dengan Laode yang simpatik dan penuh pengertian itu. Warni benar-benar bahagia. Tekad dan keyakinan yang kuat untuk mengentaskan penduduk setempat dari kebodohan dan keterbelakangan membuat dirinya begitu disegani dan dihormati oleh berbagai kalangan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama.
Memasuki tahun kesepuluh, sebuah peristiwa besar terjadi. Saat itu, di Jakarta pecah demonstrasi besar-besaran menurut rezim yang lama lengser dari panggung kekuasaan. Tak lama kemudian, bola reformasi menggelinding ke seluruh penjuru Tanah Air. Rakyat yang selama ini tertekan tiba-tiba berubah bagaikan kuda liar, larut dalam eforia. Rakyat merasa bebas untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri.
Imbas reformasi menembus ke tempat Warni bertugas. Penduduk asli yang selama ini merasa dirampas kekayaannya oleh kaum pendatang tiba-tiba saja menuntut keadilan secara sepihak. Entah dihasut siapa, warga asli tiba-tiba berubah. Secara berkelompok mereka beramai-ramai mendatangi pemukiman para pendatang sambil membawa senjata tajam. Gedung-gedung milik pemerintah dibakar, gedung sekolah dihancurkan, toko-toko dijarah, pemiliknya dianiaya. Termasuk juga kebun kopi milik Laode yang siap dipanen, dijarah beramai-ramai. Kebaikan Laode dan pengorbanan Warni terhadap penduduk setempat sudah tidak dianggap. Berkali-kali keluarganya diteror.
Aparat pemerintah dan keamanan gagal mengendalikan ulah beringas penduduk setempat. Keadaan itu membikin kaum pendatang geram. Mereka bertekad menyatukan diri untuk membalas tindakan penduduk setempat yang dinilai sudah di luar batas. Kaum pendatang mempersenjatai diri. Pertikaian terbuka tak dapat dihindari. Korban berjatuhan di sana sini. Kaum pendatang dan penduduk setempat sama-sama kalap. Akal sehat dan nurani terbang entah kemana.
Suasana perkampungan benar-benar mencekam. Denting senjata tajam, suara tangis, dan jeritan histeris membahana, membelah langit, membelah hati nurani. Setiap hari selalu saja ada korban yang terbunuh atau terluka parah, meregang nyawa terkena sabetan senjata tajam. Darah segar tercecer di mana-mana, di depan pintu rumah,di perkebunan, di ladang, di tepi hutan, bahkan di tempat ibadah. Sudah puluhan nyawa melayang, menjadi korban pertikaian sia-sia.
Warni terguguk di kamarnya. Hatinya pedih teriris-iris. Laode, suaminya, kini entah berada dimana. Warni hanya bisa mengurung diri di rumah dengan kedua anaknya, tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Tiba-tiba saja Warni ingin pulang ke Jawa. Ia sudah demikian rindu hidup di kampung halamannya yang tenteram. Menyatu bersama orang tua dan sanak saudaranya. Namun, ia sangsi, apakah ia masih bisa diterima di tengah-tengah keluarganya, terutama ayahnya.
Sementara itu, di luar rumah, kecamuk pertikaian masih terus berlanjut. Bau anyir darah terbang menusuk hidung. Warni gusar. Ia makin panik ketika pintu rumahnya mendadak digedor-gedor orang dengan paksa, ditingkah langkah-langkah kaki dan teriakan orang memanggil-manggil nama suaminya dengan kasar. Entah, tiba-tiba saja Warni merasakan rumahnya diselubungi hawa kematian. ***
Kendal, Desember 2000
(Nova, No. 676/XIII- 11 Februari 2001)

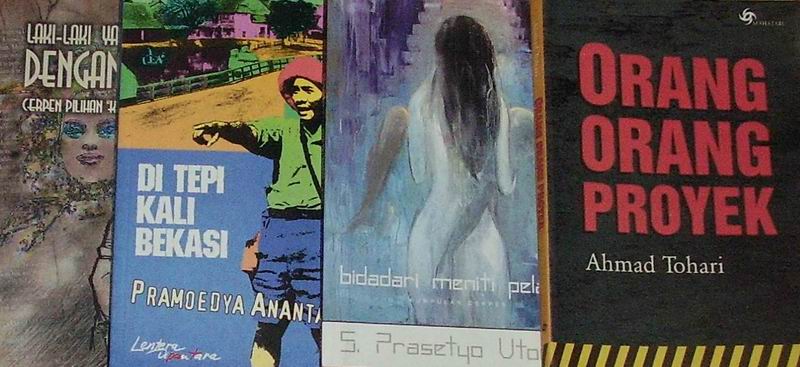
sungguh perasaan
yang benar”
membuat perasaan tak enak hati
yang pasti…
Warni oh warni. karaktermu sungguh membuatku penasaran membaca artikel ini hi..hi…