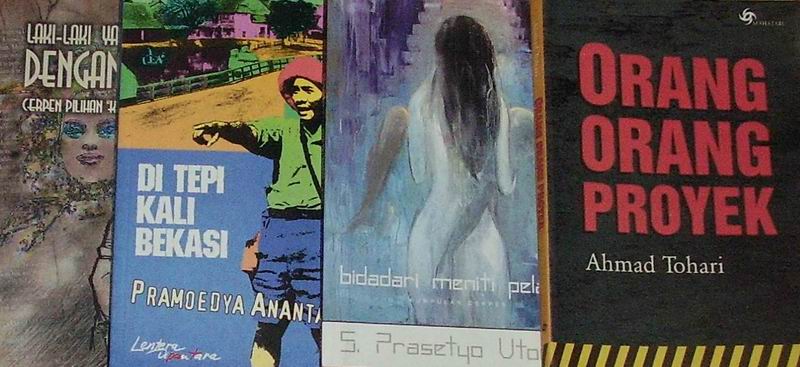Cerpen Yanusa Nugroho
Dimuat di Jawa Pos (01/10/2010)
(Kepada: Sujiwo Tejo, Ags Arya Dipayana, dan Nanang Hape)
”BULAN purnama,” begitu bisik seekor musang, sesaat ketika hendak menggigit leher ayam jantan muda itu, ”…memberimu pesona luar biasa. Sungguh malang, makhluk di bumi ini yang tak bisa bahkan menyaksikan cahayanya. Seperti kau ini…” Lalu musang pun tergelak-gelak penuh kemenangan.
”Dunia ini sungguh adil. Di malam hari, kau dibutakan, sementara mataku dinyalangkan. Alam menjadikanmu sebagai santapanku. Hahahahaha… Sejak matahari tenggelam, kau buta. Dan aku yakin benar bahwa kisah tentang rembulan yang kini tengah bertengger megah, cantik, mempesona itu, belum pernah kau dengar sama sekali.
Makhluk malang. Tapi, barangkali saja, kau sedikit lebih beruntung daripada cacing. Dia bahkan tak bisa membedakan cahaya matahari dan bulan… Hahahahahahahaa…”
Mendidih darah muda ayam jantan itu, demi mendengar penghinaan yang melumuri jiwanya. Dia, keturunan ketujuh Sawung Galih, ayam petarung paling ditakuti dan disegani di zamannya, tak bisa menerima kenyataan dihina oleh seekor musang. Darahnya mendesir, menjalari seluruh tubuhnya.
Dan pelahan, kekuatannya pulih, setelah beberapa saat lalu bagai remuk ditubruk si musang celaka. Tajiku, taji Sawung Galih dan di sana menderas daya penghancur lawan. Jika dalam sekali tendang, kau tak hancur, jangan sebut aku keturunan Sawung Galih.
***
Maka, kisah taji Sawung Galih pun kembali mengharum di antara mereka. Jago-jago petarung dari berbagai daerah merasa gentar setiap mendengar kisah bagaimana sepasang taji itu berhasil mencungkil sepasang mata musang. Ke mana pun dia pergi, tak ada yang berani menatapnya, kecuali –tentu saja– para betina, yang diam-diam berharap dapat menikmati kejantanannya.
Kokoknya akan membangunkan matahari dan kepak sayapnya membuat jago-jago lain memilih mencari kutu. Lehernya besar, kokoh dengan bulu-bulu merah darah berkilau-kilau ditimpa cahaya matahari. Paruhnya runcing, nyaris tak ada lekukan. Sepasang matanya nyalang, seakan menyelidik siapa yang bersikap menantang. Seekor ayam kate, diam-diam telah menyiapkan sebuah balada untuknya, namun yang selalu merasa gagal menemukan kata-kata.
***
Namun, itu semua dinikmatinya hanya ketika matahari masih menguasai bumi. Manakala senja turun, dan hanya keremangan yang melingkupi sepasang matanya, Sawung Galih –akhirnya nama itulah yang dikenakan kepadanya– merasa kesepian. Aneh, kisah rembulan purnama yang dituturkan si musang beberapa waktu silam itu, selalu hadir ketika senja membayang.
Mungkinkah ini semacam kutukan? Bangsa ayam tak bisa menikmati indahnya purnama? Diam-diam, dia mencoba mengingat-ingat dongeng induknya, yang selalu berkisah tentang siapa Sawung Galih dan bagaimana kehebatan ayam jantan petarung itu di zamannya. Dongeng itu akan mengantarkannya pada mimpi indah, di balik kehangatan sayap induknya.
Namun, memang sangat jarang kata ”bulan” muncul dari mulut induknya. Kalau pun ada, tentu hanya digunakannya sebagai bahan ejekan bagi kaum pungguk.
”Tapi, apakah ibu pernah melihat bulan?” tanyanya suatu kali dulu.
”Untuk apa? Apakah matahari tak cukup baik bagimu? Tidur! Kau harus malu jika saat ini matahari masih mendengar suaramu,” ujar induknya seraya merapatkan sayap-sayapnya.
Bangsa ayam ditakdirkan untuk hanya mengenal matahari dan meniadakan bulan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia menjadi terheran-heran ketika suatu ketika –tanpa sengaja– mendengar percakapan dua tikus muda dari balik reruntuhan kayu, yang berkisah tentang gemerlapnya bintang-bintang mengelilingi bulan. Dia sendiri tak paham setiap kata yang diucapkan, namun anehnya, keindahan yang diungkapkan para tikus itu seperti mendapatkan jalannya sendiri hingga sampai di pemahamannya yang paling dalam. Ayam jantan itu menghela napas.
Entah mengapa, Sawung diam-diam merasa iri pada kaum jangkrik, yang selalu menyanyi memuja-muji purnama. Setiap malam, begitu senja lenyap digantikan gelap, kaum jangkrik dengan riang gembira menyanyikan lagu. Mungkin juga mantra bagi hadirnya rembulan.
Pernah dia bertanya kepada seekor jangkrik yang saat itu nyasar.
Setelah paham bahwa si Sawung tak mungkin bisa mematuknya, timbullah keberanian si jangkrik. Dia pun menjawab setiap pertanyaan Sawung –yang dirasakannya sebagai ketololan kaum ayam.
”Kau pikir, kami menyanyi setiap malam untuk apa, kalau bukan demi munculnya purnama?”
”Apakah dengan begitu dia akan muncul?”
”Hahahaha… bodoh betul kau Sawung. Tentu saja tidak. Itu sebabnya kami terus menyanyi. Dan akan tetap menyanyi ketika pada hari ke empatbelas dia menampilkan keindahannya yang sempurna. Ah, aku harus mengirimkan bunga duka cita untuk kebodohanmu. Hahahahahaha…krik!”
”Jaga mulutmu! Kalau saja…”
”Apa? Kau mau apa? Di arena laga –aku tahu– kaulah pemenangnya. Namamu mengharum di seantero dunia… ya, aku tahu. Tapi, bagiku, kau tak ada artinya, karena kau bahkan tak tahu apa itu keindahan. Hahaha… krik…krik…krik…”
”Ajari aku,” gumamnya.
Si jangkrik terdiam tiba-tiba. Bagaimana mungkin sesosok jagoan mau tahu tentang keindahan, apalagi belajar dari seekor jangkrik? Di kejauhan, nyanyian jangkrik melaut bunyinya, menusukkan sepi di jiwa sang petarung.
***
Sejak pertemuannya dengan jangkrik, Sawung makin kelihatan murung. Ada yang tiba-tiba dirasakannya sebagai sebuah tusukan. Puluhan bahkan ratusan kali robekan taji lawan pernah dirasakannya, namun tak ada yang menyamai rasa sakit yang disebut kesepian.
Si ayam kate berusaha menghiburnya, dia pun menyanyi, ”O pahlawan, kepak sayapmu benteng bagi kaum betinaaaaa… keeok!” Si kate menjerit, Sawung menggamparnya.
”Apa yang salah Sawung?”
”Berisik!”
”Oh, aku tahu, aku tahu… Mmmm… Sunyiiii… Keook!” Si kate terjungkal, kepalanya berkunang-kunang, namun dia tak bisa mengatakan bahwa kunang-kunang saat itu indah.
***
Keindahan rembulan, yang tak pernah disaksikannya, tiba-tiba menguasainya. Seperti sesuatu yang sebenarnya sudah ada namun tak pernah dipedulikannya. Sejak hari itu Sawung seperti linglung, di arena sabung dia seperti limbung. Tajinya sesekali mungkin merepotkan lawan, namun itu karena lawannya sudah gentar sebelum bertanding. Sawung sendiri pikirannya melambung, mencoba mencari sesuatu yang belum pernah disaksikannya. Dia seperti meninggalkan raganya, melayang jiwanya entah ke mana.
Cahaya yang tak pernah kusaksikan itu, yang memancar dari cerita mereka, menghancurkanku, meremukkanku hingga tak bisa kukenali siapa diriku lagi. Akan kucari kau, akan kutemukan kau, tak peduli walau sembunyi di kerak bumi sekalipun.
Akan kutelusuri malam demi malam, dengan segenap kebutaanku, seumur hidupku, mencari dan menemukanmu. Jika kau bersembunyi di balik matahari, maka akan kuhancurkan dia dengan tajiku. Jika kau berlindung di balik mendung, akan kusapu mendung dengan sepasang sayapku. Kokokan panjangku akan membelah petir dan membuatnya tak lebih dari sekadar percikan api tungku.
***
”Sawung, Sawung, Sawung!” teriakan-teriakan itu menggema memberinya semangat bertarung. Beberapa betina memamerkan pinggulnya, memberinya gairah kehidupan.
Sesaat Sawung seperti kembali ke bumi, dan sepijar kekuatannya menyala.
Tubuhnya melompat, sayapnya membutakan mata dan sepasang tajinya bergantian menembus leher lawan. Sorak-sorai menggema, si lawan sekarat.
Sawung tegak, mengepakkan sayap dan berkokok panjang. Dia dengan gairah kemenangannya melompat tinggi nyaris terbang. Melayang tubuhnya, sebelum akhirnya hinggap di semak-semak.
Akan kucari kau, jika perlu kubalik seisi dunia ini.
”Sudah kau temukan, apa yang kau cari?” Tiba-tiba sebuah suara berat, tua dan putus asa menegurnya.
Sawung terhenyak. Hanya selangkah di depannya, seekor musang tua dengan sepasang mata butanya tengah duduk di kerimbunan semak. ”Aku tak bisa melihatmu, tetapi bukan berarti aku tak bisa mengendusmu.”
”Haha… musang tua, dendammu belum padam juga.”
”Apa pedulimu? Apakah sudah kau padamkan dendammu dalam mencari keindahan itu?”
”Bulan?”
”Lidahmu sudah cukup fasih mengeja namanya. Namun, kurasa, kau baru sebatas mengeja dengan benar, kau belum siap menghadapi keindahan itu sendiri.”
”Akan kucari di mana pun dia bersembunyi!”
”Tak mungkin kau mampu.”
”Jelaskan, mengapa aku tak mampu.”
Musang menarik napas dalam-dalam, menoleh ke kiri. Sepi. ”Dengar, anak tolol. Apa yang kau gunakan untuk mencarinya? Coba jawab pertanyaan sederhana ini.”
”Tajiku akan mengoyak semua yang melindunginya. Sayapku akan menyibak segala yang melingkupinya.”
”Hmm… angkuh sekali. Kau pikir keindahan yang memancar dari bulan purnama adalah sebutir beras? Sawung, Sawung… ternyata kau bahkan lebih dungu dari yang kukira.”
”Apa maksudmu?”
”Kau pikir bisa kau taklukkan jarak semesta ini dengan sepasang sayapmu, yang bahkan tak sekuat pipit ketika melayang? Kau anggap bisa kau belah tabir keindahan dengan sepasang tajimu? Kau bahkan tak tahu apa-apa tentang sesuatu yang kau hadapi, tetapi suaramu seakan mampu membelah langit! Sadarlah bangsa rabun, kau tak akan bisa menemukan keindahan jika masih menggunakan cara bodohmu itu.”
***
Untuk kesekian kalinya, Sawung termenung. Tak disangkanya sama sekali, dia mendapat pelajaran penting dari bangsa pemangsanya.
”Ajari aku menemukan keindahan itu,” ucapnya lirih dan putus asa.
Musang tergelak, tegak, dan lari menjauh –tentu setelah beberapa kali menabrak sesuatu. Dari kejauhan tiba-tiba musang berteriak, ”Carilah di balik keangkuhan jiwamu. Sanggupkah kau menghancurkan ke-aku-anmu?”
***
Sejak pertemuannya dengan musang tujuh hari lalu, Sawung makin murung, terlalu suka merenung dan mengurung dalam kesunyiannya. Telinganya mulai ditulikan dari teriak tantangan, bahkan tajinya diam-diam dikeratnya. Dia tak makan dan tak minum, tubuhnya merapuh, sayapnya melumpuh. Dalam usia keemasannya, dia seperti lebih tua seratus tahun. Seluruh bulu merah yang membuat para betina termimpi-mimpi, kini tampak seperti puluhan lintah gemuk yang menggelayuti leher kurusnya. Dia tengah menghancurkan dirinya sendiri, mencoba mencari keindahan yang bersembunyi di balik keangkuhannya.
Suatu malam, di hari keempat belas, keindahan itu datang menjemputnya. Sawung tak bisa berbuat apa-apa. Jiwanya kosong, dan karenanya dia mampu menerima keindahan itu seutuhnya. Air matanya berlinang, dia pun merasaan kebahagiaan yang belum pernah dialami sebelumnya.
***
Bangsa ayam berduka. Mereka menemukan jasad Sawung tergolek merana. Si ayam kate menyanyikan baladanya, ”Telah gugur jagoankuuuuuu…. Tu… keook!”
”Berisik!”
Dan malamnya, jutaan jangkrik melantunkan kidungnya, kaum musang menebarkan keharuman tubuhnya, dan bangsa pungguk terdiam seribu bahasa, menatap entah apa di atas sana. ***
Pinang, 982